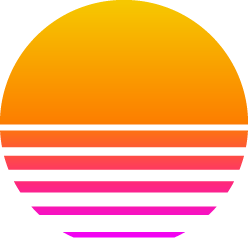Saya sering mendapatkan pertanyaan masuk, entah lewat situs Anandastoon ini atau lewat Instagram, yang bertanya apakah saya tertarik untuk membahas politik.
Saya sering mendapatkan pertanyaan masuk, entah lewat situs Anandastoon ini atau lewat Instagram, yang bertanya apakah saya tertarik untuk membahas politik.
Sebetulnya jawabannya bukan iya atau tidak, namun saya akan jelaskan mengapa saya memilih jawaban tersebut.
Politik itu sendiri sebenarnya dapat dihubungkan sebagai ‘seni’ untuk memperoleh kekuasaan (untuk memimpin suatu negara/wilayah).
Jadi saat kita berbicara politik, sebenarnya kita bicara tentang kepentingan pejabat yang sedang atau akan mengatur kehidupan kita dalam bernegara sehari-hari.
Inilah yang membuat saya enggan berbicara politik kepada orang-orang yang bahkan tidak mengerti apa itu politik.
Ibaratnya, mengapa saya harus berdebat tentang kalkulus dan trigonometri dengan orang yang bahkan masih tidak paham operasi perkalian dan pembagian?
Saya tidak berkata bahwa saya paham politik, tidak sama sekali, tapi…
Masih banyak masyarakat kita yang memilih pemimpin hanya berdasarkan suka dan tidak suka, serta cenderung subjektif.
Misalnya, saya memilih A karena doi suka blusukan, atau saya memilih B karena doi pandai mengolah kata. Banyak orang yang masih terjerumus kepada drama dan pencitraan yang dibuat para pemimpin, tanpa ingin mengetahui apa saja manfaat dan hasil kerja yang telah dihasilkan oleh para pemimpin tersebut.
Maksud saya, tidak mengapa si A gemar blusukan dengan syarat ia memperbaiki akses jalan untuk masyarakat. Atau tidak mengapa si B pandai mengolah kata jika banyak fasilitas umum yang ia perbaiki.
Namun yang justru terjadi adalah terpecah belahnya masyarakat menjadi beberapa kubu politik. “Cebong” dan “Kampret” adalah salah satu dari bencana politik yang terjadi sebab banyak kalangan masyarakat prematur yang sudah berani membahas politik.
Dear, look, saat kita berbicara politik, secara langsung dan tidak langsung maka kita sedang membicarakan dampak yang akan dirasakan oleh seluruh warga negara, bukan cuma untuk segolongan saja.
Saya justru lebih tertarik membicarakan kita sebagai rakyat itu sendiri dibandingkan dengan membicarakan pejabat saat berbicara masalah politik.
Tentu saja alasannya karena para pejabat yang sering kita bicarakan itu bukanlah alien, melainkan mereka dulunya berada di tengah-tengah kita, yang kemungkinan sifatnya sama persis seperti kita.
Maka dari itu, saat kita mengeluhkan sifat-sifat pejabat yang negatif, sebenarnya sifat itu bukanlah milik pejabat, melainkan milik sebagian besar kita.
Inilah mengapa ada pernyataan, “pemimpin adalah cerminan rakyatnya.” Apalagi negara kita menganut prinsip demokrasi yang sudah jelas “dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat”, tidak ada kata “pejabat” atau “aparat” di dalamnya, semuanya murni “rakyat”.
Contohnya, saat ada seorang pejabat korup yang sulit ditangkap, bahkan pelapornya yang justru dipenjara, itu bukanlah sifat yang hanya dimiliki pejabat, itu adalah sifat kita.
Dulu sewaktu di sekolah, kegiatan mencontek adalah sebuah hal yang lumrah. Jika ada seorang murid melapor, maka murid tersebut akan dimusuhi hingga diteror oleh hampir seluruh kelas.
Atau solidaritas pekerja yang tidak memiliki kinerja yang bagus dan cenderung merugikan perusahaan tempat mereka bekerja. Jika ada yang mencoba menegur salah seorang pekerja tersebut, maka seluruh solidaritasnya akan menyerang si penegur.
Contoh lain, jika ada pejabat yang berprinsip, “Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?” Sekali lagi, itu bukan hanya sifat pejabat, itu juga adalah sifat kita.
Berapa banyak dari kita yang bekerja tidak sepenuh hati, bahkan cenderung sejadinya, namun kita justru berdalih, “masih mending dikerjain” atau “yang penting ada” atau bahkan “gak bersyukur banget sih”.
Mungkin melihat kenyataan ini, sebagian orang bukannya introspeksi diri, mereka justru kembali berdalih, “Kan nggak semuanya begitu…”
Dear, jawaban “kan nggak semuanya begitu…” adalah jawaban yang paling ugal-ugalan, paling sembrono, dan paling masa bodoh yang pernah saya dengar.
Apakah harus menunggu 100% dahulu baru kita peduli? Padahal di atas 20% saja itu sudah sangat banyak.
Nila setitik saja sudah merusak susu sebelanga, apalagi jika nilanya diguyur.
Sayangnya saat kita berbicara kepentingan masyarakat luas, masih sangat banyak yang justru berbicara masalah personal yang jelas-jelas jauh dari nilai objektif.
Hal ini diperparah jika agama sudah dilibatkan ke dalam ranah politik.
Sebelumnya saya paham bahwa agama pun mengajarkan kaidah atau syariat berpolitik. Tetapi dalam praktiknya, agama hanya dijadikan sebagai simbol semata, jarang sekali yang menyinggung bagaimana kiat agama dalam mengatur urusan politik.
Nilai-nilai agama justru dijual dan dijadikan pangsa pasar oleh para pejabat sebagai kampanye dan masih sangat banyak orang-orang yang terjerumus ke dalamnya.
Jadi, mengapa saya masih harus berbicara politik dengan orang-orang seperti ini?
Jika memang saya harus berbicara politik, saya akan berbicara tentang nilai manfaat yang dihasilkan oleh para pejabat tersebut seperti hasil kinerja, perbaikan layanan, dan sejenisnya.
Saya justru lebih menaruh perhatian kepada para masyarakatnya. Ingin seperti apa pemimpin yang akan dilahirkan dari sebuah golongan masyarakat yang semaunya, tidak ingin ada usaha ekstra, dan nilai manfaat mereka masih sangat rendah?
Mengapa negara maju minim koruptor? Mudah, karena para pemimpinnya lahir dari masyarakat yang bukan hanya pekerja keras, namun akhlak dan kepedulian mereka sudah sangat luhur. Jangankan kepada sesama manusia, mereka pun menaruh perhatian lebih kepada alam sekitar.
Kesimpulannya, bagaimana sekarang dengan kita? Apakah akan menghasilkan pemimpin yang baik jika ditinjau dari akhlak dan hasil kerja kita sendiri?
0 Jejak Manis Ditinggalkan
Ke Atas