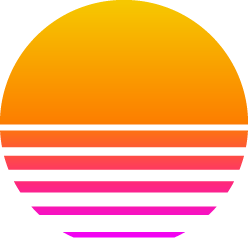Kemacetan, kemacetan… ternyata istilah “tua di jalan” itu memang nyata adanya. Semakin hari kendaraan bermotor semakin menjamur sedangkan hal tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan volume jalan. Akhirnya, untuk menempuh suatu tujuan harus mendapatkan ekstra waktu hingga berjam-jam.
Jakarta, salah satu kota paling macet di mana berton-ton emisi terbuang percuma. Kemacetan memiliki dampak yang buruk bagi perekonomian, lingkungan, bahkan hingga kepada para pengendara itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurai kemacetan tersebut. Dari berbagai solusi yang ada, yang paling terasa adalah ‘pemaksaan’ para pemilik kendaraan pribadi untuk beralih moda ke transportasi umum.
Kebijakan itu tampaknya tidak begitu bersambut gayung oleh para pengendara yang sudah nyaman dengan kendaraan pribadinya, dan berkilah, “Kami sudah bayar pajak kendaraan, mengapa harus dipaksa naik kendaraan umum?”
Saya mencoba menggarisbawahi pernyataan “Kami sudah bayar pajak kendaraan, mengapa harus dipaksa naik kendaraan umum?”. Dan memang sangat menarik untuk dibahas apakah pernyataan tersebut benar, atau tidak.
-
Stigma mengenai pajak
Saya pernah berbincang dengan seseorang yang kepayahan sendiri karena mencicil kendaraan bermotor lebih dari satu. Keluhannya bertambah saat dia sadar dia juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak kendaraan-kendaraannya. Padahal, gajinya perbulan masih tidak pasti, kebanyakan masih dibawah 2 juta rupiah per bulan.
Bahkan kendaraan pribadi yang tidak terpakai pun, tetap dikenakan pajak. Rumah pribadi yang tidak terpakai pun, tetap dikenakan pajak. Namun tipikal manusia pada umumnya, mereka melulu terlalu menjunjung tinggi hak-haknya sehingga mengabaikan kewajibannya.
Saya katakan kepada orang tersebut, bahwa mengapa ia tidak menabung Rp50.000,- per bulan untuk mencicil pajaknya? Ia bisa membayar cicilan kendaraan-kendaraannya, mengapa dia tidak sanggup membayar pajaknya yang tidak terlalu jauh dengan jumlah cicilan kendaraan-kendaraannya?
Lagi, jika memang kendaraan yang dia perlukan cukup satu, mengapa harus membeli banyak. Jika yang dia perlukan hanya matik, mengapa yang ia beli adalah kopling. Gengsi, gaya, gaul, saya menyebutnya 3G, yang pada akhirnya berujung galau, gundah, dan gulana.
“Bergayalah sesuai isi dompetmu.” Kata-kata mendiang Bob Sadino tersebut seringkali diabaikan.
Pajak, bagaimanapun, akan kembali manfaatnya bagi yang telah menunaikan kewajibannya. Jangan khawatir akan dikorupsi pejabat-pejabat pemerintahan, karena para pengendara pun masih sangat banyak yang melakukan korupsi di jalanan. Ingat, pemimpin adalah representasi dari rakyatnya.
Setidaknya, dari pajak itulah berbagai subsidi dapat dinikmati.
-
Solusi ada bersama pengorbanan
Mengapa memilih menggunakan kendaraan pribadi? Terutama bagi pengendara roda dua, saya yakin sebagian besar jawabannya adalah masalah efisiensi waktu. Lebih cepat, dan praktis. Bahkan tidak puas dengan bonus waktu yang mereka dapatkan, beberapa dari mereka juga cenderung membabat waktu orang lain demi kepentingannya sendiri. Benar, menerobos lampu merah, trotoar, jembatan penyebrangan, dan busway.
Pada akhirnya, setiap kendaraan terjebak macet. Baik kendaraan roda dua, maupun roda empat, penyebabnya karena masalah kuantitas dan volume. Banyak yang teriak ingin jalan dilebarkan atau dibangun flyover/underpass. Padahal, apakah jalan Jendral Sudirman dan Hj. Rasuna Said belum cukup lebar? Nyatanya dua jalan itu masih jadi biang kemacetan. Bahkan flyover pun sudah dibangun di mana-mana, yang pada akhirnya, mengurangi estetika kota dan justru menambah kemacetan karena jalanan yang lancar mengundang orang lain untuk berbondong-bondong melewatinya.
Solusi yang saat ini dapat diandalkan adalah memaksa masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, namun hal tersebut mendapat banyak penolakan dengan dalih pajak di atas. Perlu diketahui, jika ada belum ada solusi yang dapat dipikirkan, maka solusi yang ada adalah solusi terbaik.
-
Gengsi, siapa takut?
Alasan masyarakat pengguna kendaraan pribadi masih tidak ingin beralih ke moda transportasi umum adalah ketidakpastian waktu menunggu, dan jauhnya jarak dari rumah ke stasiun atau halte terdekat. Belum lagi, yang seharusnya tampil modis ketika sampai di tempat tujuan, mereka khawatir kondisi mereka sudah tidak lagi prima karena naik angkutan umum, berdesakan, dan penuh keringat.
Padahal, jika dihitung kembali, dalam satu bus dapat menampung dari 40 hingga 80 orang, bahkan dalam satu gerbong kereta bisa mencapai 200 orang. Belum lagi, pemerintah mensubsidi kebanyakan tarif untuk angkutan umum untuk mengundang setiap orang agar beralih moda. Layanan pengaduan pun mereka kencangkan jika suatu saat para pengguna menemukan suatu hal yang mengurangi kenyamanan mereka.
Penumpang-penumpang kereta dan bus banyak yang memakai dasi, blazer mentereng, dan sepatu-sepatu mengkilap. Bayangkan jika para penumpang yang berjumlah ribuan setiap harinya itu memilih menggunakan kendaraan pribadi, maka kemacetan apalagi yang diinginkan?
Orang-orang yang enggan, lebih memilih kecepatan 20 km/jam dibandingan berdesak-desakkan tetapi lebih dahulu sampai. Hal tersebut tidak dibudayakan dari awal sehingga keengganan dan gengsi sudah mengakar dalam diri orang-orang tersebut.
-
Tepisan dan kesimpulan
Mengapa masih diwajibkan membayar pajak kendaraan ketika masyarakat dipaksa untuk menggunakan kendaraan umum? Saya tekankan itu hanyalah sebuah kalimat pembelaan diri karena ‘takut’nya naik kendaraan umum atas dasar stigma-stigma mengenai kendaraan umum yang telah disebutkan di atas.
Tahu film Crayon Shinchan? Benar, bapaknya punya mobil. Namun kesehariannya dia justru pergi ke kantor dengan berdesak-desakan di kereta. Kapan mobilnya dipakai? Ketika sedang dalam acara liburan keluarga, atau pada malam hari di mana kendaraan-kendaraan umum sudah selesai operasi.
Teman saya punya mobil dua buah, namun justru dia lebih memilih moda kereta listrik sebagai sarana transportasi sehari-hari karena waktunya lebih berharga daripada yang lain. Teman saya juga sangat taat dalam membayar pajak. Karena macet itu pilihan, setiap area pasti memiliki batas tampung maksimal.
Jadi seharusnya pertanyaannya dibalik, “Mengapa punya kendaraan jika tidak mau membayar pajaknya?”
0 Jejak Manis Ditinggalkan
Ke Atas