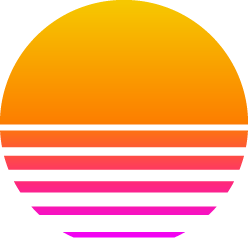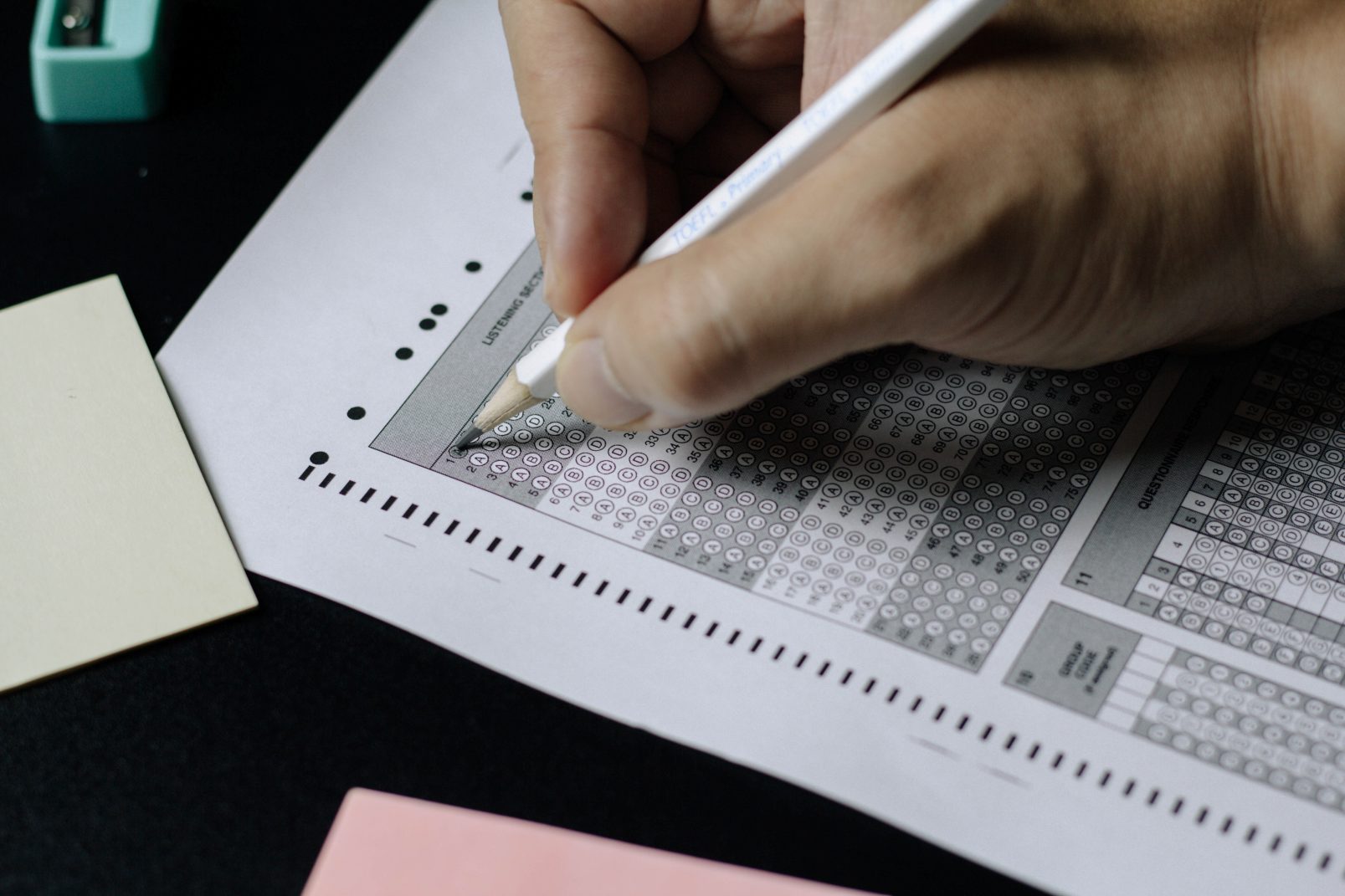
Sewaktu mentri pendidikan merencanakan tentang penghapusan ujian nasional (UN), saya merasakan banyak sekali gegap gempita yang terjadi di kalangan masyarakat.
Bahkan sesi komentar di salah satu judul berita yang memuat pernyataan tersebut dipenuhi dengan komentar yang sebagian besar mendukung.
Namun, dear pembaca, saya memohon diri untuk mengajukan pendapat berbeda.
Apa ini artinya saya tidak setuju jika ujian nasional dihapus? Benar, saya tidak setuju jika ujian nasional dihapus.
Setidaknya ada tiga alasan pendukung mengapa saya menolak penghapusan ujian nasional.
UN sebagai tes kepribadian
Saya mengerti jika banyak sekali siswa yang memiliki kecemasan berlebih pada detik-detik ingin dilaksanakannya ujian nasional. Saya sendiri pun pernah mengalami hai itu.
Apalagi saat kita disuguhkan kenyataan bahwa ujian nasional menjadi salah satu faktor penentu kelulusan, saya yakin hampir seluruh murid akan dilanda berbagai macam kekhawatiran di saat-saat ingin menghadapi ujian nasional.
Di masa-masa itu, jam sekolah ditambah untuk evaluasi pembelajaran selama tiga tahun, dengan dilakukan pembahasan seluruh mata pelajaran yang akan diujikan saat UN.
Dear, bagaimana jika sekarang kita ubah paradigma mengenai UN. Ada baiknya jika menteri pendidikan dan segenap masyarakatnya tidak mengganggap UN sebagai evaluasi akhir, melainkan menjadi ‘tes kepribadian’. Lho, maksudnya?
Begini, saya memahami jika tidak semua murid menguasai seluruh mata pelajaran. Apalagi jika ada murid yang lamban dalam melakukan berbagai hitungan dan matematika.
Dengan UN yang beralih fungsi menjadi tes kepribadian, setiap siswa dapat mengetahui bayangan bagaimana ia melanjutkan jenjang pendidikan dan karirnya nanti.
Misalnya, seorang siswa ternyata memiliki nilai UN yang buruk pada matematika dan IPA, namun meraih predikat membanggakan pada nilai bahasa Inggrisnya. Siswa tersebut menjadi tahu ia harus mengambil jurusan kuliah seperti hubungan diplomatik atau multimedia yang tidak melulu bersinggungan dengan matematika, misalnya.
Para orang tua juga wajib diajarkan agar lebih menerima kemampuan anaknya daripada melihat hasil dari nilainya. Dengan bimbingan dari orang tua akan hasil dari ijazah anaknya yang potensial, anak menjadi termotivasi untuk meraih karir yang ia inginkan yang juga memiliki dampak positif bagi orang tuanya.
Dengan demikian secara tidak langsung, budaya mencontek akan tergerus dengan sendirinya karena berkurangnya tekanan dan gengsi dari sekitar untuk tetap mendapatkan nilai yang tinggi untuk segala bidang.
Evaluasi tiga tahun
Salah satu sebab penolakan saya akan penghapusan UN adalah karena setiap segala sesuatu perlu dilakukan evaluasi.
Dear, look, selama ini orang tua kita ‘menghanguskan’ puluhan juta demi menyekolahkan kita. Lalu apa hasil yang dapat kita berikan kepada mereka? Apakah pendidikan itu hanya sekedar untuk memusnahkan kewajiban semata?
Kita marah jika kita telah membayar mahal sebuah produk namun produk tersebut ternyata tidak diuji dan rawan rusak. Begitu pun dengan pendidikan.
Contoh lain, ada beberapa dari kita kecewa saat seorang santri yang telah bertahun-tahun mengenyam pendidikan pesantren namun pengetahuan agamanya buruk, bahkan kewajiban syariatnya masih banyak ia tinggalkan.
Kita mungkin berkata, “Selama di sekolah atau di pesantren ngapain aja?”
Inilah yang membuat saya menolak dengan sangat penghapusan UN.
Namun seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ujian nasional ini hanya sebagai evaluasi ulang. Meskipun mungkin banyak mata pelajaran yang tidak akan teraplikasikan di dunia nyata, setidaknya itu dapat membentuk kebiasaan berpikir dari para murid.
Saya pun selama jadi programmer, baru menyadari ternyata ada beberapa algoritma yang dulunya berasal dari pelajaran matematika yang saya pelajari sedari SMP dulu.
Begitu pun dengan pelajaran lain seperti PPKn/PMP, Bahasa Indonesia/Inggris, Fisika, Kimia, Akuntansi, hingga Sejarah. Ada beberapa pengetahuan yang ternyata selama ini saya abaikan, dan sedikit demi sedikit baru mendapatkan kasus nyatanya di kemudian hari.
Bukankah lebih banyak ilmu yang dimiliki seseorang akan membuatnya lebih baik dan lebih memiliki dasar untuk dikembangkan dan diterapkan di dunia nyata daripada yang tidak?
Ingat, puluhan juta uang orang tua dialokasikan untuk menyekolahkan kita, dan apa bentuk dari rasa menghargai kita akan uang mereka?
Bukan hanya itu, puluhan guru yang telah bersusah payah mengajarkan kita berbagai macam ilmu, menghadapi kelakuan kita yang beragam, dan menyediakan waktu ekstra untuk mendengarkan pertanyaan kita, apa timbal balik yang kita berikan kepada mereka?
Saya ingat guru matematika saya pernah berkata, “Ibu tidak menuntut kalian untuk memahami semua ini, minimal 20% dari kalian memahami pelajaran ibu saja, ibu sudah sangat bahagia.”
Pembentukan watak
Sekarang lihat kepada barang elektronik kita, entah televisi, smartphone, laptop, komputer, hingga kendaraan bermotor, dari mana itu diproduksi? Sebagian besar kita mungkin akan menjawab Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan negara-negara maju lainnya.
Sekarang pertanyaan menarik muncul. Apakah negara-negara maju tersebut memiliki ujian nasional atau ujian akhir sekolah? Tentu. Meski memang sebutannya berbeda-beda.
Intinya, setiap negara maju yang saya ketahui memiliki ujian akhir atau final exam.
Kita sendiri sering melihat saat menonton kartun atau anime Jepang, ada beberapa episodenya yang menunjukkan karakter ceritanya belajar hingga dini hari menjelang dilaksanakannya ujian-ujian tersebut.
Persiapan dalam menghadapi ujian akhir dapat membentuk watak seseorang untuk menghadapi dunia yang katanya ‘keras’ ini.
Saya bahkan sempat terluncurkan pertanyaan menggelitik mengenai penghapusan UN, “Apakah yang menolak UN adalah bukan orang rajin dan giat belajar?”
Orang yang selalu menghindari ujian dapat dikatakan orang yang cenderung mencari celah-celah aman dalam kehidupannya. Tentu saja ini sangat berbahaya sebab orang yang tidak siap menghadapi hal-hal yang dituntut dalam kehidupan, cenderung akan menjadi parasit bagi orang lain.
Sebagai penekanan, orang yang rajin saat sekolah pun masih dapat menjadi pengangguran, tetapi ingat, kemungkinannya sangat kecil dari mereka. Berbeda dengan mereka yang sewaktu sekolah tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah dan sering bolos.
Akhirnya bukan hanya sekali dua kali saya dengar orang-orang yang hingga kuliah masih sering bermalas-malasan hingga suka menitipkan kehadiran kepada temannya, ia menghadapi berbagai kesulitan saat mencari pekerjaan, jangankan pekerjaan bergengsi.
Maka dari itu, tuntutan agar belajar lebih rajin saat ingin menghadapi UN bukanlah untuk mendapatkan nilai sempurna, melainkan sebagai pembentukan kebiasaan kita setelah selesai menempuh masa pendidikan dan mulai berhadapan dengan dunia nyata.
Orang-orang yang telah terbiasa rajin dan gigih sedari kecil biasanya akan lebih banyak mencari gengsi lewat upaya ekstra mereka, mereka akan merasa diri mereka begitu rendah jika ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha.
Inilah mengapa negara-negara maju yang notabene masyarakatnya banyak yang giat dan gigih cenderung minim koruptor.
0 Jejak Manis Ditinggalkan
Ke Atas