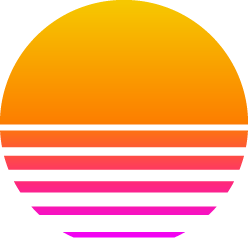Di era yang serba canggih, segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan efisien.
Namun, dari semua kemudahan dan efisiensi yang kita rasakan berkat kecanggihan ini justru muncul sebuah paradoks.
Paradoks Jevons namanya, tentang:
Fenomena di mana peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya justru menyebabkan peningkatan konsumsi total sumber daya tersebut, bukan penurunan.
Contoh singkat yang mudah kita pahami dari paradoks Jevon ini adalah,
Rem kendaraan diciptakan untuk mengurangi laju kendaraan. Tetapi kenyataannya justru membuat para pengemudi semakin meningkatkan kecepatannya karena sudah ada rem yang akan menghentikan lajunya.
Tanpa rem, bagaimana pengemudi bisa mengebut? Jadi seolah tujuan penciptaan rem bukan untuk mengurangi laju kendaraan, melainkan meningkatkannya.
Inilah paradoks yang menarik untuk kita bahas. Apalagi di tengah kecanggihan dan kemudahan yang kita rasakan ini, jumlah paradoksnya semakin banyak.
Saya kumpulkan lima buah paradoks Jevons ini yang benar-benar terjadi di antara kita, pada era yang serba efisien ini.
Listrik hemat energi
Pada tahun 2021, saya menginap di rumah teman. Beliau sudah jauh lebih tua dari saya dan sudah berkeluarga. Maka dari itu, meski teman, saya memanggil beliau dengan sebutan “Bapak”.
Waktu itu sudah pukul satu dini hari, dan kami masih belum tidur. Saya melihat beliau meninggalkan ruang keluarga dengan televisi LED besar yang masih menyala.
Tidak terputar tayangan apa pun di TV tersebut, hanya tampil halaman utamanya saja.
Saya bertanya kepada beliau, “Pak, itu nggak dimatiin TVnya?”
Beliau jawab, “Biarin aja Nda, itu udah hemat energi.”
Entah, saya merasa agak kurang nyaman dengan jawaban itu.
Maksudnya, karena saya dibesarkan di tengah keluarga yang lumayan ketat dengan penghematan, jadi disiplin untuk mematikan sesuatu yang tidak terpakai sudah mendarah daging dalam diri saya.
Jadi bukan masalah hemat energinya, namun lebih ke disiplinnya.
Dalam kasus lain, saya sendiri seringkali pulang malam saat gedung perkantoran sudah gelap.
Pemandangan yang saya saksikan sebelum pulang, adalah lampu dan bahkan AC yang tidak dimatikan (kami berkantor di coworking space dengan banyak perusahaan lain dalam satu lantai terbuka), serta piring-gelas yang masih berserakan di meja kerja luar dari pegawai lain yang juga pulang larut sebelum saya.
Petugas kebersihan dan OB sudah pulang sedari sore, jadi tidak ada yang mematikan listrik hingga membereskan peralatan makan yang masih berada di meja kerja.
Di sinilah paradoksnya, disiplin dan kepedulian dapat memudar saat konsekuensinya telah samar atau hilang.
Dahulu, banyak orang yang begitu disiplin dalam menggunakan listrik (dan air) karena jika tidak, tagihannya bisa membengkak.
Sekarang, efisiensi energi listrik sudah dapat meminimalisir tagihan, sehingga setiap orang seolah lebih bisa menghambur-hamburkan listrik semau mereka.
Dan perilaku ini selain menggerus disiplin penggunaan listrik, juga bisa menggerus kepedulian dalam hal lainnya, termasuk mengurangi kepekaan manusia.
Kendaraan pribadi berlimpah
Memiliki kendaraan pribadi adalah kebutuhan sekunder manusia, atau bahkan juga sekaligus kebutuhan tersier.
Dengan kendaraan pribadi, bukan hanya terpenuhi kebutuhan transportasi kita, melainkan juga kebutuhan gengsi sebagian dari kita untuk kita tunjukkan kepada kolega dan sanak keluarga.
Hari ini, menjamurnya sistem angsuran bisa membuat hampir setiap kalangan mendapatkan kendaraan pribadi mereka.
Kemudahan mendapatkan kendaraan pribadi justru menghasilkan dua buah paradoks Jevons, dari segi fisik dan mental.
Paradoks fisik, seperti yang kita sudah tahu, semakin banyak penggunaan kendaraan pribadi bisa memperparah polusi udara sampai kelangkaan bahan bakar.
Polusi udara dan kelangkaan bahan bakar akhirnya bisa diatasi dengan kehadiran kendaraan listrik. Namun itu justru menimbulkan masalah lain, yakni meningkatnya angka kemacetan.
Paradoks mentalnya, karena hampir setiap orang bisa mendapatkan kendaraan dengan mudah, termasuk kendaraan mewah, itu tentu dapat menghilangkan nilai dari kendaraan mewah itu sendiri.
Beberapa teman saya dari kalangan menengah ke atas pada akhirnya membeli sepeda motor yang biasa saja selama berfungsi dengan baik (yang penting bisa gas dan rem).
Saat saya tanya alasan tidak membeli kendaraan yang lebih mewah, jawaban mereka sederhana,
“Buat apa beli yang bagus-bagus kalau sekarang tukang ojeg aja udah bisa punya yang sama?”
Apalagi hari ini banyak sekali peristiwa kendaraan bagus tanpa plat nomor belakang. Kabarnya karena pemiliknya menghindari cicilan supaya tidak dipantau oleh para penagih hutang yang biasa kita sebut dengan mata elang.
Luasnya layar smartphone
Tahun 2012, saya ingin mengganti HP jadul saya yang masih menggunakan papan tombol angka dengan HP layar sentuh seperti Android.
Alasan di balik keinginan saya itu sederhana, karena saya lumayan hobi mengutak-atik sesuatu, terlebih saya juga senang menulis, saya ingin lebih ekspresif lagi dengan layar yang lebih besar itu dan papan ketik yang sudah QWERTY.
Sebelumnya pada HP sebelumnya yang fiturnya serba terbatas, saya lumayan mengisi waktu saya dengan hal-hal unik seperti membuat musik lewat Nokia Composer, bahkan hingga beberapa animasi GIF sendiri.
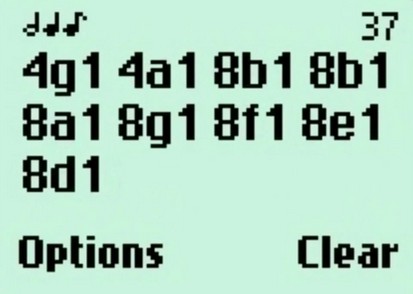
Nokia Composer
Harapannya, saya bisa lebih produktif lagi saat telah memiliki smartphone dengan layar yang lebih lebar seolah seperti laptop dalam genggaman.
Betul bahwa saya sempat membuat beberapa postingan blog lewat smartphone terbaru saya, namun itu hanya bertahan beberapa bulan saja.
Hingga kini, waktu saya sepertinya lebih banyak habis menyelami drama media sosial daripada benar-benar melakukan hal produktif yang dulu pernah saya dambakan di smartphone.
Canggihnya AI
Saya berpikir bahwa kecerdasan buatan atau AI adalah salah satu fitur puncak yang pernah dibuat oleh manusia.
AI bisa mencarikan jawaban langsung dalam hitungan detik, memecahkan masalah, bahkan hingga membantu penelitian para ilmuwan dan melakukan otomasi pekerjaan yang kita tidak perlu melakukan hal yang sama berkali-kali.
Apalagi dengan layanan gratis AI yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, tujuannya adalah untuk meringankan aktivitas para penggunanya.
Tetapi yang terjadi hari ini, kehadiran AI justru membuat kebanyakan orang terpecah menjadi dua golongan:
- Mereka yang menggunakan AI sebagai jalan pintas mencari validasi seperti mengklaim karya instan, dan
- Mereka yang menggunakan AI untuk menghasilkan hal-hal yang tidak perlu hingga menguji AI untuk hal yang tidak berguna.
Saya sendiri meski seorang programmer, namun jarang menggunakan AI untuk menghasilkan kodingan untuk saya. Saya lebih sering berbincang dengan AI tentang praktik terbaik dalam penyelesaian masalah.
Sesekali bahkan saya memberikan solusi yang benar kepada AI yang saya pakai karena AI itu sendiri mengakui bahwa data yang ia dapatkan mungkin tidak secepat perubahan versi dari teknologi yang saya sedang gunakan.
AI pun berterima kasih atas kontribusi saya dalam perbaikan tersebut jika suatu saat ada programmer lain yang mengalami masalah serupa.
Kembali lagi kepada kenyataan, yang saya temukan baik di media sosial dan juga di lapangan, bahwa mencari programmer yang bisa memahami pondasi atau fundamental kian sulit. Bahkan untuk hal dasar saja, mereka yang mengaku programmer harus menyalin kodingan dari AI.
Analoginya, mobil yang bisa berkendara otomatis justru membuat orang yang tidak mahir mengemudi merasa telah setingkat dengan supir yang sudah berpengalaman di berbagai medan jalan.
Atau, desainer yang hanya lewat template merasa sudah dapat menghasilkan karya yang sama profesionalnya dengan desainer ahli.
Cukup mengerikan jika kita pikir kembali.
Sistem irigasi mumpuni
Dahulu, banyak kampanye membatasi jumlah anak lewat program KB karena khawatir di masa mendatang, overpopulasi akan mengakibatkan bencana kelaparan karena tidak seimbangnya jumlah manusia dengan sumber makanan.
Namun hal itu tidak pernah terjadi. Makanan baik nabati atau pun hewani tetap berlimpah, restoran dan pedagang kaki lima semakin menjamur, dan harganya sangat terjangkau walaupun hanya sebatas mi instan.
Teknologi pengairan atau irigasi, dan pengelolaan makanan yang semakin modern, ternyata berhasil meminimalisir bencana kelaparan dan menjaga stok makanan umat manusia yang jumlahnya kian banyak di seluruh belahan dunia.
Sekali lagi, hal ini melahirkan masalah baru.
Tidak jarang saya perhatikan, banyak orang yang dengan mudahnya membuang-buang makanan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Saya sendiri pun termasuk meski hanya sesekali.
Misalnya, saya sering melihat orang yang memesan nasi goreng dengan porsi satu piring penuh, hanya untuk ia makan beberapa sendok saja.
Saya bisa memahami saat ada orang meninggalkan makanan apabila memang porsinya terlalu banyak atau ia ternyata tidak suka. Tetapi saya hanya menemukan kejadian buang-buang makanan ini semakin terlalu sering. Benar-benar ditinggalkan begitu saja.
Bahkan pinalti di restoran all you can eat yang memberi peringatan bahwa makanan yang tersisa akan dikenakan denda setiap seratus gram pun tidak mempan menegur mereka.
Kesimpulan
Inti dari paradoks Jevon ini sebenarnya hanya satu, dan itu pun sebenarnya diungkap oleh AI itu sendiri. Pernah saya tulis di sini.
Kita menginginkan efisiensi untuk membuat hidup lebih mudah, namun itu hanya membuat orang menjadi tidak menghargai proses.
Akibatnya, banyak orang yang jadi menggampangkan hingga memandang sebelah mata sebuah perjuangan. Padahal, kemudahan yang kita dapatkan berasal dari proses panjang yang sangat melelahkan, sampai menguras harta, tenaga, waktu, dan pikiran.
Namun seperti itulah manusia. Saat sebuah fitur dalam diri kita tidak kita nyalakan, maka fitur tersebut akan menjadi tumpul.
Orang yang terlalu sering mengandalkan transportasi online, maka fitur navigasinya akan memudar sehingga sulit untuk menemukan arah atau sekadar membaca peta.
Orang yang terlalu sering mengetik, maka kemampuan tulisan tangannya akan berkurang drastis.
Dan orang yang terlalu sering mengonsumsi video-video pendek di media sosial, kemampuan literasinya akan menjadi rendah.
Masih banyak lagi kasus yang perlu jadi perhatian untuk ke depannya.
Bukannya kita tidak boleh menikmati kemudahan, namun kita juga perlu memahami fundamentalnya supaya kecanggihan tersebut terasa manfaatnya oleh kita dan tidak menjadikan kita lemah.
Terakhir, mempertahankan kualitas diri memang selalu menjadi bagian yang paling sulit.
0 Jejak Manis Ditinggalkan
Ke Atas