
Pernah mengenyam bangku sekolah menengah di Majalengka, sebagai orang Betawi saya cukup ‘fasih’ berbahasa Sunda.
Namun banyak orang yang justru menganggap saya lebih mirip robot daripada seorang manusia betulan saat berbicara bahasa Sunda.
“Ai maneh teh asa teu pantes nyarios Sunda kos kitu…”
Saya membatin, “Deuh nya duka teuing… Wayahna da…”
Yang sempat menggelitik saya dari beberapa bahasa daerah di Indonesia, ada grammar unik yang mungkin tidak ada bahasa daerah di negara lain yang punya, saya tidak tahu.
Grammar unik tersebut adalah bahasa halus dan bahasa kasar. Uniknya, divisi atau kasta bahasa ini tidak sama dengan bahasa formal dan informal, ini lebih kepada standar moral yang dimiliki oleh seseorang. Beberapa bahasa daerah di Indonesia memiliki ‘fitur’ ini, termasuk bahasa Betawi.
Seperti misalnya, untuk penyebutan “saya”, beberapa bahasa daerah memiliki bahasa halus, dan kasar, atau bahkan bahasa sedang masing-masing. Seperti bahasa Sunda yang mana “saya” dapat diterjemahkan “abdi” atau “sim kuring” dalam bahasa halus, “uing” atau “urang” dalam bahasa menengah, “aing” dalam bahasa kasar.
Akan sangat kurang ajar jika berbicara dengan orang yang lebih tua dengan pemilihan bahasa yang paling kasar. Namun akan terlalu canggung jika memilih bahasa yang paling halus dalam obrolan sehari-hari.
Yang menjadi perhatian di sini adalah, apa poin adanya fitur seperti ini?
Saya akan membahasnya dengan cukup singkat saja. Kalau kita lihat, bahasa Arab misalnya, seluruh penyebutan kata ganti orang kedua “kamu” atau “anda” di luar masalah gender, semuanya akan dipukul rata dengan sebutan “anta” (sekali lagi, mengabaikan gender).
Benar, dalam bahasa Arab, entah itu kepada yang lebih muda, sebaya, lebih tua, atau bahkan nabi dan Tuhan sekali pun, semuanya tetap menggunakan “anta”. Tidak ada pengistimewaan khusus dalam penyebutan ‘kasta’ bahasa.
Mungkin jika mengacu kepada bahasa formal dan informal atau bahasa karya seni sastra, dalam bahasa Indonesia untuk penyebutan “kamu”, ada “anda” untuk yang lebih formal, dan ada “engkau” yang biasanya digunakan dalam karya-karya sastra, termasuk penyebutan orang yang diagungkan dan Tuhan.
Begitu pun bahasa Spanyol yang pernah saya pelajari, untuk penyebutan “kamu” ada “tú” untuk formal, dan “usted” untuk informal.
Namun semua itu sebenarnya hanyalah masalah perbedaan formal dan informal, sama sekali bukanlah termasuk pengkastaan bahasa mana yang halus atau mana yang kasar.
Sejujurnya, jika bukan karena warisan dari kekayaan budaya, saya tidak pernah mengerti untuk apa ada pembagian kasta bahasa ini.
Maksud saya, mengapa perlu ada bahasa kasar untuk negeri yang terkenal dengan budaya ramah tamah ini? Mengapa tidak dipaksa saja untuk menggunakan bahasa halus atau setidaknya menengah saja jadi tidak perlu lagi ada bahasa kasar.
Lagipula, saya ingat almarhumah nenek saya dahulu yang pernah sakit hati dipanggil dengan bahasa kasar dengan orang yang baru beliau kenal. Ternyata, bahasa kasar di daerah tersebut ternyata adalah bahasa halus, padahal masih satu bahasa. Apa hal ini tidak akan menimbulkan kesenjangan bahasa?
Dalam lingkup bahasa Indonesia itu sendiri, sekalipun saat kita sedang benar-benar marah atau mengutuk seseorang, kata ganti yang paling resmi digunakan hanya sampai kepada penyebutan “kamu” atau “dia”, tidak ada penyebutan yang lebih rendah dari itu.
Jadi sekali lagi, saya mengagumi dengan warisan budaya leluhur yang sangat kaya dan beragam, namun bukan berarti kita tidak boleh kritis bukan?
Saya sekali lagi hanya memikirkan, jika seseorang hidup di negara timur yang katanya sarat dengan tatakrama dan budi pekerti luhur, mengapa ia tidak pernah diajarkan untuk menggunakan bahasa yang paling halus saja.
Adapun masalah kekhawatiran budaya pengkastaan bahasa ini akan punah jika kita tidak pernah menggunakan bahasa kasar, sebenarnya bahasa Indonesia itu sendiri banyak sekali ejaan-ejaan yang memang sudah usang atau tidak dipakai lagi. Saya ingat dulu selain dari akhiran “-lah” dan “-kah”, kita pernah mengenal akhiran “-tah”.
Beberapa buku bahasa Indonesia kurikulum 1994 yang masih menggunakan sistem caturwulan pernah membahas penggunaan beberapa ejaan yang kini bahkan sudah tidak pernah dipakai lagi. Saya lupa apa saja selain dari akhiran “-tah” itu.
Jadi, mengapa seseorang tidak menyeragamkan pengkastaan bahasa dan memilih bahasa yang paling halus atau setidaknya menengah saja dari masing-masing bahasa daerah yang memiliki ‘fitur’ pengkastaan bahasa tersebut? Ejaan yang usang tetap akan bagian dari warisan sejarah, hanya tidak pernah digunakan kembali demi menghindari penyalahgunaan kasta bahasa.
Bagaimana menurut kalian?
Klik di mari untuk menuju halaman diarinya.
1 Jejak Manis Ditinggalkan
Minta Komentarnya Dong...
Ke Atas
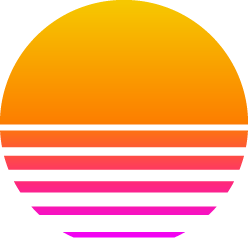














Oh iya, kalau dalam basa Sunda disebutnya undak-usuk basa, jadi seperti budaya yang harus dilestarikan aja gitu. Tapi sepertinya prakteknya udah agak memudar ya.