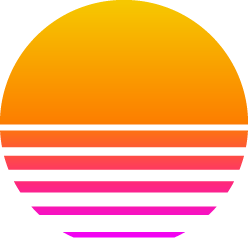Malam itu saya penasaran dengan suatu kejadian sains, saya lupa apa tepatnya, kalau tidak salah berkaitan dengan pertanyaan seputar bagaimana rasa bahagia dapat dibentuk dalam tubuh. Jadi saya cari lewat Google. Saya kemudian tahu bahwa itu adalah tanggung jawab hormon endorfin dan serotonin, tapi bukan itu yang mengklik saya malam itu.
Malam itu saya penasaran dengan suatu kejadian sains, saya lupa apa tepatnya, kalau tidak salah berkaitan dengan pertanyaan seputar bagaimana rasa bahagia dapat dibentuk dalam tubuh. Jadi saya cari lewat Google. Saya kemudian tahu bahwa itu adalah tanggung jawab hormon endorfin dan serotonin, tapi bukan itu yang mengklik saya malam itu.
Saya melihat penulis artikelnya memiliki gelar Ph.D. yang merupakan salah satu gelar paling bergengsi di luar sana. Artinya, dengan gelar atau titel yang dimiliki penulis tersebut, saya memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dengan artikel yang saya baca pada malam itu karena memang ditulis oleh ‘ahli’nya.
Sebenarnya berdasarkan pengalaman saya sejak beberapa tahun lalu, saya sangat menyayangkan beberapa sarjana yang hanya memandang gelarnya tidak lebih dari hiasan semata. Bahkan tidak sedikit para sarjana yang pada akhirnya hanya bekerja di bidang yang anak lulusan SMA pun sangat mampu untuk melakukannya.
Lalu apa artinya puluhan juta uang SKS yang telah terbakar demi meraih titel tersebut?
-
Saat titel tidak lebih dari sebatas “pembantu rumah tangga”
Agak disesalkan jika saya ingat banyak sekali orang-orang yang saya kenal memberikan laporan mengenai dirinya atau teman-temannya yang menganggap kuliah hanya untuk mendapatkan gelar secara formalitas belaka.
Karena gelar atau titel merupakan bagian dari gengsi, yang mana terkadang orang lain mempermasalahkan hal ini atas diri kita.
Memang dia gelarnya apa? Sarjana lulusan apa? Dan pertanyaan-pertanyaan berisik lainnya. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa gelar bukan lagi diperlukan saat akan melamar kerja, namun juga telah menjadi syarat sah untuk dapat melamar kekasih dan menikah bagi sebagian orang.
Sebenarnya saya senang dengan tuntutan yang cukup ekstrem tersebut untuk memacu anak-anak muda agar mereka menuntut ilmu dengan jenjang yang lebih tinggi, tetapi faktanya hal itu mereka peroleh justru hanya untuk formalitas dan meraih kepercayaan diri berlebih, setidaknya sebagian besar dari mereka.
Semua itu terbukti dengan maraknya cerita sang mahasiswa kupu-kupu (kuliah pulang-kuliah pulang) dan peristiwa penitipan absen sang mahasiswa. Bahkan jasa penerbitan ijazah palsu masih laris hingga kini di bawah permukaan apa pun yang dapat terlihat.
Sekali lagi, hanya demi gelar yang mereka pandang tidak lebih dari sekedar formalitas dan gengsi.
-
Saat titel menagih kembali janjinya
Saya entah mengapa memiliki rasa bahagia dengan sarjana-sarjana produktif yang dengan titelnya mereka dapat menambal beberapa keraguan yang selama ini menghantui masyarakat. Entah keraguan tersebut berupa isu, misteri sosial, atau hanya stigma semata.
Contohnya, saya gemar membaca tulisan-tulisan religi untuk memuaskan rasa penasaran saya dengan agama saya sendiri, yaitu Islam. Saya begitu senang saat saya tahu penulisnya memiliki gelar “Lc.” atau ditambah “M.A” yang berjejer dengan namanya. Setidaknya saya dapat tahu bahwa artikelnya ini dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis atau ilmiah.
Mengapa?
Karena tentu saja orang yang meraih gelar tersebut telah mengalokasikan waktu, tenaga, dan biayanya untuk pendidikan selama minimal tiga tahun di saat orang-orang di sekitarnya hanya stuck dengan rutinitas hidupnya. Bahkan para sarjana itu dulunya hingga menghabiskan waktu melanjutkan pendidikan di luar negeri, jauh dari keluarga dan kerabat.
Para mahasiswa telah berjuang siang dan malam memenuhi standar-standar yang disebut SKS, melakukan banyak penelitian ilmiah, harus menguasai minimal mengerti beberapa kaidah dasar dalam keilmuan khusus tersebut, menulis beberapa jurnal, dan wajib melewati serangkaian ujian tertulis maupun lisan sebelum akhirnya mereka terbekali dengan tahun-tahun pendidikan yang telah dilewatinya.
Intinya, dengan para sarjana yang telah ‘digoreng’ selama beberapa semester tersebut, mereka seharusnya sudah semakin matang untuk mengaplikasikan ilmunya di ranah publik, minimal dalam bentuk karya opini atau artikel.
-
Saat titel dapat mencampakkan sang pemilik
Pernah di jejaring sosial saya melihat dua foto yang diposting untuk membandingkan perilaku lulusan sarjana dengan mereka yang mungkin tidak sekolah.
Saya lihat dari foto pertama yang menggambarkan lulusan sarjana sedang bersepeda di sembarang tempat dan tidak pada jalurnya sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Satunya lagi ada foto orang-orang udik yang bersepeda teratur dengan rapi di tepi jalan.
Lebih miris lagi, caption foto tersebut bertuliskan, “Lihat kelakuan lulusan sarjana dengan orang yang mungkin cuma lulusan SD!”
Saya memahami maksud baik dari foto tersebut untuk memecut orang-orang yang berpendidikan tinggi untuk memberikan contoh terbaiknya kepada orang-orang yang bukan. Sungguh hal yang memalukan jika sampai terjadi yang sebaliknya.
Namun, saya cukup prihatin jika titel yang telah diraih para sarjana tidak lagi membuat orang lain menghormati mereka, bahkan ada yang memandang para sarjana lebih rendah dari orang-orang yang hanya lulus sekolah dasar. Ini cukup menjadi sebuah ‘bencana’ jika para sarjana bertitel ‘gagal’ untuk membangun kesan yang baik di masyarakat.
Padahal, suatu daerah atau bahkan negara begitu memiliki harapan yang besar kepada mahasiswa yang telah berhasil menimba ilmu lebih sebagai orang yang dipercaya untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu mengapa justru bisa terjadi hal yang bertolak berlakang dari itu?
-
Kesimpulan
Titel atau gelar sarjana dapat menjadi penunjang hidup untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Tetapi di samping itu, gelar sarjana pun menjadi sebuah tanggung jawab besar dalam hidup pemiliknya. Ia dituntut untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan titelnya tersebut di luar gengsinya.
Sekarang lihatlah bagaimana kejamnya gelar-gelar kesarjanaan tersebut melakukan ‘balas dendam’ kepada sang pemilik gelar karena gagal untuk meraih simpati dari masyarakat dari semua ilmu yang telah dituntutnya selama itu.
Jangan sampai uang yang telah dihabiskan berjuta-juta, waktu yang telah terbuang demi tuntutan pendidikan yang mencekik bertahun-tahun, ternyata semua itu hanya menghasilkan orang-orang yang pada akhirnya ‘diludahi’ masyarakat secara tidak langsung. Sangat disayangkan jika endingnya seperti itu.
Semoga kita tidak sampai menjadi demikian. Karena bagaimana pun, derajat orang yang berilmu pastinya lebih tinggi daripada yang tidak, itulah sebabnya mereka yang berilmu dituntut untuk lebih bijak dan dapat meraih kepercayaan dari masyarakat di sekitarnya.
Tidak ada satu pun dari gelar sarjana yang ingin dianggap hanya sebagai formalitas dan syarat sah, karena konsekuensi yang akan dilakukan oleh gelar-gelar tersebut kepada pemilik-pemiliknya sangat tidak main-main.
0 Jejak Manis Ditinggalkan
Ke Atas