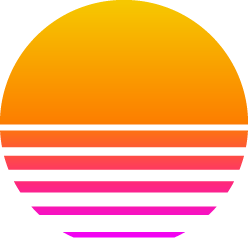Demo mahasiswa yang berakhir ricuh hingga menimbulkan korban jiwa pada Agustus 2025 lalu cukup menyita perhatian, termasuk diri saya pribadi.
Lalu mengapa judul artikelnya seolah mengisyaratkan bahwa saya tidak ingin turun ke jalan lagi? Bukankah menyuarakan suara di negara demokrasi ini sangat krusial?
Unjuk rasa merupakan salah satu sarana penyaluran aspirasi, bagaimana pun metodenya.
Bahkan tidak terbatas pada negara demokrasi, menyampaikan pendapat supaya didengar juga merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial.
Saya pernah ikut aksi demonstrasi pada tahun 2017 silam, yang menyoal kasus Gubernur Jakarta tentang “al-Maidah” pada saat itu.
Tujuan saya berpartisipasi adalah agar gubernur tidak lagi menyinggung hal-hal yang sangat sensitif seperti ini, sebab bukan ranah beliau. Hanya saja…
Hanya saja saat orator mulai menyuarakan agar gubernur harus turun dari jabatannya hingga ada yang mengisyaratkan untuk membunuhnya, bagi saya itu sudah di luar cakupan tujuan saya melakukan aksi unjuk rasa.
Saya langsung memutuskan ‘kabur’ dari kegiatan demonstrasi tersebut.
Seiring jalannya waktu, semakin saya mencoba peduli dengan masalah sosial politik yang terjadi di sekeliling saya, cara pandang saya dengan lingkungan hingga negara semakin berubah.
…yang menjadikan saya mungkin tidak pernah ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi.
Sebab akibat yang simpel
Saya mengetahui bahwa THR (Tunjangan Hari Raya) yang kita terima adalah hasil dari demonstrasi para buruh tahun 1950 silam, dan saya cukup berterima kasih dengan itu.
Maksudnya, siapa yang tidak senang mendapatkan gaji ke-13? Demonstrasi pun bisa mendapatkan timbal balik yang positif pula, dan hasilnya bisa bertahan hingga kini.
Formulanya sederhana, semakin banyak orang yang menyuarakan, artinya pemangku kebijakan bisa semakin tahu bahwa itu sudah sangat mendesak dan bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan jika tidak diatasi segera.
Waktu itu saya sedang menunggu Transjakarta, dan tidak senang dengan waktu tunggu yang begitu lama hingga satu jam lebih menyebabkan penumpukan di halte.
Saya yang ‘meledak’ pada saat itu tiba-tiba menyarankan penumpang lain agar ikut memberikan komplain ke saluran aduan Transjakartanya langsung, sebab jika hanya saya sendiri yang melapor mungkin bisa dengan mudah diabaikan.
Manusia memiliki rasa takut dengan tekanan dan ancaman, apalagi jika berasal dari banyak orang.
Begitu pun dengan aparat pemerintahan kita yang kemungkinan didominasi dengan orang-orang yang merasa aman dengan jabatan mereka, terkadang perlu juga mendapatkan sebuah gertakan jika cara yang baik-baik sudah tidak lagi mengena.
Tapi… kenapa justru saya sudah menetapkan bahwa saya kemungkinan tidak ingin melakukan aksi demonstrasi lagi?
Secercah pendahuluan
Jika kita berbicara politik, kebanyakan hari ini saya sudah menutup telinga dengan itu.
Saya sudah banyak sekali menulis tentang politik di kategori Opini di blog Anandastoon ini dan saya rasa cukup.
Sejujurnya, pikiran saya sudah terbuka mengenai keadaan sosial politik di Indonesia ini sejak 2015. Yakni saat saya mendapatkan tawaran untuk membuat sistem administrasi di sebuah pabrik.
Seorang ibu, yang merupakan presdir di pabrik tersebut menahan amarah dan tangis beliau sembari menunjukkan kondisi pabriknya yang berantakan.
Para buruh di pabrik itu, 70% menurut si ibunya, selalu mencuri waktu saat jam kerja bahkan hingga mencuri bahan baku. Pernah sampai ada buruh baik yang melapor bahwa ada barang baku yang disembunyikan di kolong rak gudang hingga seberat empat ton.
Para pegawai kantornya pun seolah sama saja, bahkan merugikan perusahaan karena selalu mengambil aset berupa ATK dan mereka jual kembali. Mereka beralasan kertas cepat habis karena sering terjadi kekeliruan kalkulasi. Saya pernah buat artikelnya di sini.
Maka dari itu, si ibunya memanggil kami untuk membuat sistem untuk memonitoring kinerja para pegawainya yang kebanyakannya bobrok.
Tetapi apa yang terjadi? Kami justru dimusuhi oleh para pegawai termasuk buruhnya. Kemudian mereka sebagian besar melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan sebab mereka tidak ingin kinerja mereka dipantau oleh aplikasi.
Ini tidak terjadi sekali dua kali. Saya yang bekerja di bidang aplikasi sistem, tentu saja terkejut menemukan fenomena seperti ini. Kami ditolak hingga pernah diancam di balik layar oleh staf yang tidak ingin pekerjaan mereka dimonitor oleh apa pun.
Ternyata lumayan banyak para pengusaha yang menderita dengan perilaku para pekerjanya. Benar bahwa ada pengusaha yang kikir, buruk, dan jahat, tetapi kita sekarang sedang membicarakan pengusaha yang baik, yang membangun perusahaan dari hati.
Padahal para staf atau karyawan mereka masih dari kalangan rakyat biasa, belum sampai menjadi pejabat pemerintah. Namun waw, PRnya sudah semenyedihkan ini.
Para buruh dan karyawan rajin pun ikut tertekan dengan perilaku rekan mereka yang meresahkan. Sayangnya, mereka yang rajin jumlahnya begitu sedikit sehingga luput dari sorotan masyarakat.
Semenjak saat itu, pandangan sosial politik saya berubah. Jiwa overproud saya luntur. Ternyata banyak yang harus kita benahi dari akarnya jika ingin tumbuh pohon politik yang baik.
Bahkan bukan dari akar saja, melainkan dari kualitas tanahnya pula.
Ujian kedewasaan
Saya menutup telinga setiap pembicaraan politik Indonesia. Bahkan seringnya saya kembalikan lagi ke lawan bicara tentang keadaan yang paling dekat dari sisi mereka dahulu.
Bukan sekali dua kali saya menemukan orang yang hobi membicarakan politik namun kinerja mereka sendiri justru amburadul, tidak peduli sekitar, mengganggu orang lain, bahkan sampai melakukan korupsi (nilep) uang perusahaan.
Saya jadi curiga kepada beberapa orang yang membicarakan politik hanya untuk memenuhi nafsu mereka untuk menyalahkan pemerintah saja demi menutupi perilaku mereka yang tidak lebih baik.
Menyalahkan orang lain itu “nikmat” bukan? Apalagi memang pemerintah kita memiliki banyak hal untuk kita lemparkan berbagai kesalahan.
Sejujurnya saya menjaga jarak dengan orang yang membicarakan politik hanya untuk menyalahkan pemerintah saja. Saya khawatir memang sudah tabiat mereka yang hobi menyalahkan orang lain. Bisa jadi suatu saat kesalahan saya pun akan menjadi topik mendidih bagi mereka.
Atau jangan-jangan memang sudah jalannya pemerintah atau wakil rakyat kita kerap memiliki kinerja yang minim agar jadi hiburan bagi orang-orang yang hobi salah-menyalahkan itu.
Saat ada rakyat hobi menyalahkan pemerintah, maka pemerintah pun hobi menyalahkan rakyatnya. Ternyata budaya salah-menyalahkan sudah mendarah daging di negara ini.
Bagaimana kita dapat memutus lingkaran setan tersebut? Kapan terakhir kali kita melakukan intospeksi diri dan menjadi lebih baik dari sebelumnya?
Apabila kita tidak terpikirkan cara untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi diri kita sendiri apalagi untuk orang lain, jangan menuntut pemerintah melakukan hal serupa. Karena sudah jelas mereka tidak dibiasakan untuk menjadi bermanfaat sejak mereka masih menjadi rakyat.
Negara yang sudah maju, yang mana para pemerintahnya sudah peduli dengan rakyatnya, maka kita lihat sebagian besar rakyatnya pun ikut tertib dan berpikiran maju juga.
Sejarah yang terulang
Pohon yang buruk akan tumbuh dari akar yang busuk atau dari tanah yang jelek pula.
Lucunya saat kita melayangkan tuntutan kepada pemerintah, kita sendiri tidak siap mendapatkan tuntutan dari orang lain.
Atau saat kita menyebutkan pemerintah antikritik, memang kapan terakhir kali kita mau menerima komplain dari orang lain?
Kita ingin mendapatkan kabar baik dari kinerja pemerintah. Tetapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Apa fitur bermanfaat terbaru yang kita hasilkan dari pekerjaan kita? Apakah ada laporan hariannya? Laporan mingguannya?
Sedari hampir sedekade lalu, saya cukup sering menggaungkan bahwa pemerintah yang kita demo dulunya hidup bersama kita juga. Lihat? Ada supir angkot bisa jadi menteri, bahkan ada tukang kayu bisa jadi presiden, kemudian kita demo mereka semua itu.
Lebih parah lagi, ada wakil rakyat yang kita demo, dulunya mereka juga aktif berdemo kepada pemerintah.
Ingat kelamnya tragedi 98? Saya yang masih balita kebetulan menyaksikan sendiri kepulan asap hitam di jalan protokol dari atap rumah saya waktu itu.
Mereka yang membakar fasilitas publik, melakukan penjarahan, bahkan menghilangkan banyak nyawa, adalah masih bagian dari rakyat pula.
Mungkin ada benarnya pula saat kita bilang ada penyusup yang menimbulkan kericuhan pada aksi unjuk rasa tersebut. Tetapi pada tahun 2020 silam, ketika demo buruh berujung ricuh hingga menghanguskan halte Bundaran HI dan Tosari yang baru saja direvitalisasi, saya melihat banyak buruh yang bersorak sorai lewat story mereka di Facebook.
Artinya, mereka secara tidak langsung termasuk yang menyetujui perusakan fasilitas umum, walaupun katanya dilakukan oleh penyusup atau entah.
Contoh lain, kasus pagar laut di kabupaten Tangerang bagian utara beberapa tahun lalu. Ternyata sesama warga dibenturkan dengan massa bayaran yang masih bagian dari warga itu juga.
Artinya, lawan kita dalam berpolitik adalah masyarakat kita sendiri.
58% ???
Saya sangat memahami bahwa sebagian besar kita tidaklah seperti itu. Saya percaya.
Kerap kita menuduh 58% dari bagian masyarakat itulah yang mengacaukan sistem politik kita. Mereka yang 58% memilih pemimpin yang tidak kita setujui, bahkan 58% itu di antaranya termasuk para buzzer pemerintah yang mendapatkan bayaran menggiurkan.
Namun apakah yang 42%nya tidak berkontribusi dalam bobroknya politik di negara ini?
Kita mulai dari yang kecil saja terlebih dahulu.
Sudah seringkali saya menyatakan bahwa benar yang 42% tidak berperilaku demikian. Namun jangan lupa bahwa ada sifat permisif atau bahkan sifat naif yang tidak kita sadari justru ikut berpartisipasi dalam korupnya sistem di Indonesia.
Tidak sedikit dari kita yang masih terkurung dalam gelembung fatamorgana bahwa masyarakat Indonesia banyak yang pintar. Namun nyatanya kita saksikan sendiri begitu minimnya jumlah pengusaha dan manajer di Indonesia yang menyebabkan meledaknya angka pengangguran.
Seperti guru SD saya dahulu bilang,
Orang Indonesia itu banyak yang pintar, namun kebanyakannya “karbitan” (belum matang)
Akui saja dahulu faktanya bahwa masih banyak masyarakat kita yang mudah diiming-imingi dan gemar melanggar peraturan. Hal ini sudah saja jelaskan secara panjang lebar pada artikel saya tentang kemiskinan mental dan ciri SDM berkualitas rendah.
Saya sendiri cukup mengernyitkan dahi dengan orang-orang yang hobi membahas politik tetapi mereka permisif dengan keadaan di sekitarnya.
Mereka seolah biasa saja tertawa-tertiwi berjalan di trotoar yang dikuasai para pemotor yang hobi membunyikan klakson dan meluapkan emosi.
Bahkan banyak perbuatan tercela orang-orang yang begitu saja dimaafkan hanya karena mereka mengaku atau terlihat sebagai rakyat kecil.
Pada akhirnya, para pembuat onar semakin menjadi-jadi karena mereka merasa mendapatkan keberpihakan dari masyarakat sedangkan mereka punya banyak solidaritas.
Bukan sekali dua kali saat saya ingin mengadukan perilaku petugas pelayanan publik yang kinerjanya tidak dapat saya tolerir, justru dihalau oleh beberapa orang hingga saya mendapatkan teror.
Ternyata kita sendiri yang menyuburkan perilaku korup tersebut hingga mereka bergabung dengan ormas tertentu, bahkan hingga mendapatkan “kursi”.
Tidak perlu membahas sekelas DPR atau menteri, kita mulai dahulu saja dari RT, RW, lurah, camat, hingga bupati atau gubernur.
Saya angkat tangan.
Intinya
Apakah saya masih akan ikut melakukan aksi unjuk rasa ke depannya?
Tergantung. Bagaimana saya ingin ikut mendemo perilaku pemerintah sedangkan sifat yang ingin saya demo ternyata banyak bertebaran di sekeliling saya?
Kita pernah berunjuk rasa secara brutal untuk menurunkan presiden kedua, tetapi presiden ketiga yang berhasil menekan harga dolar pun ternyata menjadi presiden dengan masa jabatan paling pendek sepanjang sejarah Indonesia. Jadi maunya masyarakat ini apa?
Kita benci punya pemimpin korup. Tetapi pemimpin yang tidak korup juga mungkin tidak akan sanggup memimpin masyarakat yang kebanyakannya juga korup.
Masih sangat jelas di kepala saya, saat pak Jonan membereskan KAI dan melarang pedagang asongan masuk stasiun, beberapa mahasiswa melayangkan protes karena kebijakan beliau mematikan rezeki para pedagang asongan tersebut.
Saya hanya tersenyum sinis mengetahui hal itu dan membatin, “Ke mana para mahasiswa itu sekarang? Jangan-jangan ada yang sudah jadi pejabat korup juga.”
Inilah akibatnya jika demonstran tidak memiliki koordinasi dan setiap orang dengan sembarangan bisa ikut bersuara.
Ingat insiden PT. Yihong? Insiden paling lucu bagi saya sekaligus miris. Apakah orang-orang seperti ini diizinkan menyuarakan pendapat? Itu merupakan penghinaan bagi saya jika suatu saat saya ikut berdemonstrasi.
Analogi mudahnya, para orang tua pasti akan mendengarkan tuntutan anak yang rajin daripada anak yang membangkang.
Sekarang, saya lebih memilih silent report atau melakukan aksi yang samar.
Misalnya teruntai pertanyaan, “Kenapa para pengusaha tidak berdemo saja jika merasa dizalimi pemerintah atau buruh mereka sendiri?”
Para pengusaha tidak perlu demo dengan cara turun ke jalan lagi. Mereka cukup memakai cara yang memang mereka sudah terbiasa dalam menyusun strategi bisnis mereka.
Jika mereka tidak tahan dengan perilaku para buruhnya yang berkualitas minim namun kerap melayangkan tuntutan, mereka akan mengganti buruh-buruh tersebut dengan robot dan mempertahankan buruh yang punya dedikasi.
Atau lebih parah, jika mereka sudah sangat tertekan dengan kondisi sosial politik, seperti kebijakan pemerintah yang menyulitkan, mereka cukup ‘kabur’ ke negara lain yang lebih ramah pengusaha.
Karena saya hidup di Jakarta dan menyaksikan banyak perilaku masyarakat sekitar, harap agar tidak berbicara politik dengan saya sebelum lawan bicara mengetahui alasan mengapa ada orang yang menyebut “Jakarta itu keras“.
0 Jejak Manis Ditinggalkan
Ke Atas