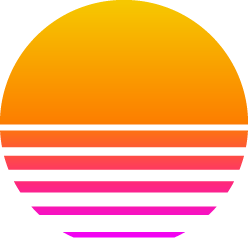Beberapa bulan lalu dari sejak saya tulis artikel ini, kepala berita di berbagai situs web penuh dengan judul yang mengabarkan bahwa banyak hari ini kaum menengah yang jatuh miskin.
Daya beli menurun menjadi sebab utamanya. Bahkan di tahun 2025 ini, semenjak dari akhir 2024 kemarin, ramai-ramai bermunculan ajakan “Frugal Living” untuk kaum menengah.
Frugal Living itu sendiri bisa berarti penghematan. Karena daya beli kaum menengah yang lesu di tengah gempuran biaya dan bayang-bayang pajak yang semakin melangit, seolah mereka ‘terpaksa’ untuk menerapkan konsep hidup yang jauh lebih hemat.
Misalnya, dengan mengurangi jatah makan, tongkrongan, hingga pariwisata.
Padahal, ada yang menyebutkan bahwa kontribusi kaum menengah bagi penerimaan negara mencapai hingga 80% lebih.
Artinya, masyarakat menengah, baik menengah ke bawah atau menengah ke atas selama masih di atas garis kemiskinan, memiliki power atau kekuatan yang menggerakkan ekonomi negara.
Hanya saja, mengapa kekuatan rakyat menengah di Indonesia yang sedemikian besarnya itu harus hilang bahkan sampai harus jatuh miskin?
Betul bahwa pemerintah memiliki andil yang besar di kasus ini. Tetapi bagaimana jika sekarang saya lebih fokus membahas kaum menengahnya itu sendiri?
Pijakan awal
Golongan menengah bagi saya adalah golongan sandwich, tergencet di antara dua golongan namun tidak mendapatkan keistimewaan dari keduanya.
Golongan menengah tidak mendapatkan banyak subsidi seperti golongan miskin, dan tidak pula mendapatkan cukup uang untuk menyejajarkan dengan golongan kaya.
Terlebih, golongan menengah seringkali tidak mendapatkan sorotan karena masyarakat banyak yang terlalu fokus entah kepada golongan bawah atau golongan atas.
Belum lagi di Indonesia, golongan menengah sebagai penyumbang pajak terbesar justru hampir tidak mendapatkan bagian dari pajak tersebut kecuali sangat sedikit. Kebanyakannya habis dikorupsi oleh kalangan atas (pejabat) dan menjadi bantuan sosial di luar subsidi untuk kalangan bawah.
Kaum menengah dapat apa? Di beberapa daerah bahkan banyak yang infrastrukturnya belum lengkap, fasilitas umum yang sering rusak, membuat berangkat dan pulang kerja menjadi tantangan tersendiri.
Padahal, kaum menengah sebenarnya hanya perlu kemudahan dan kelancaran mereka dalam beraktivitas, menjalani kehidupan normal yang aman sentosa. Mereka sudah banyak stres yang terlimpah di tempat kerja.
Saya menaruh rasa hormat kepada kaum menengah di sini yang seringkali terlewatkan kehadiran mereka di mata sebagian besar masyarakat.
Hanya saja, itu dulu. Mengapa memangnya sekarang?
Frugal yang normal
Saya penasaran dengan bagaimana teknik kaum menengah ini dalam membangun komitmen “Frugal Living” mereka. Yang ternyata, setelah saya perhatikan, sebagian besar teknik penghematan yang mereka lakukan ternyata memang sudah normal.
Segala macam normalisasi yang digembar-gemborkan, kebanyakannya memang sudah normal. Sebagian besarnya hanya mengurangi kegiatan konsumtif ke batas wajar.
Misalnya, yang biasanya menggunakan transportasi online ke tempat kerja atau ke stasiun terdekat yang kurang dari 1km, kini lebih memilih menggunakan bus atau berjalan kaki.
Atau yang biasanya sering melampiaskan emosinya dengan checkout barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting di toko online, kini mengurangi kegiatan itu semua.
Kemudian mengurangi tongkrongan, duduk di kafe yang biasanya setiap malam, kini seminggu hanya sekali atau dua kali.
Itu semua pada dasarnya memang normal, justru sepertinya bukan bentuk Frugal Living sama sekali.
Kekhawatiran dalam penurunan daya beli di sini adalah ketika masyarakat sudah semakin banyak yang tidak mampu membeli kebutuhan normal mereka dalam jumlah yang cukup.
Entah warung kelontong atau minimarket yang semakin sepi, hingga bisnis perumahan yang minim peminat. Itu semua bisa berdampak kepada pemasukan usaha yang ikut lesu, yang tentu saja bisa menimbulkan banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Betul bahwa semuanya akan berdampak kepada penerimaan pajak yang dapat membuat penerimaan negara menurun. Kita pun hampir atau bahkan semuanya kompak setuju bahwa solusi menaikkan pajak adalah tidak begitu tepat.
Jadi, saat kaum menengah banyak yang melakukan Frugal Living, justru saya setuju agar mengurangi pemborosan. Karena seandainya tidak Frugal Living pun ujung-ujungnya tetap jatuh miskin pula sebab manajemen keuangan yang buruk.
Pemilik power yang lemah 1
Kecanggihan teknologi hari ini membawa banyak kemudahan yang sangat luar biasa. Dari mulai jasa pengantar makanan, pembayaran instan, hingga transportasi via genggaman.
Hanya saja, saat ini saya ingin berbicara dampaknya. Benar bahwa tidak semuanya demikian, tetapi jikalau hanya minoritas tentu tidak perlu saya repot-repot menulis artikel ini.
Saya agak tertegun saat belum lama ini ada kampanye mengurangi asupan gula. Banyak yang seolah melihat bahwa gula sudah menjadi sejahat alkohol dan nikotin. Ada apa?
Saya membaca berita semakin banyaknya gen Z dan milenial yang terkena diabetes.
Kebetulan belum lama ini cukup sering saya melihat secara tidak sengaja dalam lift banyak pekerja yang memesan transportasi online ke tempat yang dengan mudahnya dijangkau dengan Transjakarta. Padahal, jarak dari kantor saya ke halte busway dan stasiun LRT terdekat hanya 20 meter.
Pikiran positifnya, mungkin mereka sengaja tidak menggunakan fasilitas kendaraan umum itu karena terburu-buru, memiliki trauma, atau kurang sehat.
Tetapi, pernah ada yang cerita kepada saya kalau ternyata alasannya menggunakan transportasi online adalah sekadar “malas jalan”. Meski, saya lihat trotoar di perkantoran Sudirman dan Kuningan sebagian besarnya sudah lebar dan bagus.
Begitu pun anak-anak yang menggunakan ojek online dari sekolah ke rumahnya yang hanya berjarak 300 meter. Sudah dua kali saya kedapatan ini dan bahkan anak sekolah dasar sudah banyak menggunakan sepeda motor listrik di jalanan.
Padahal dahulu, jajanan saya sewaktu masih sekolah jauh lebih parah. Minuman manis, gula biang, dan berbagai kimia buatan serta minyak jelantah menghiasi menu jajan sekolah saya saat istirahat.
Tetapi karena saya pulang sekolah berjalan kaki hingga 500 meter lebih, bahkan sampai sekarang saya masih gemar mengonsumsi manis, alhamdulillah kadar gula darah saya normal.
Gula itu sumber energi yang harus dibakar, bukan dimusuhi. Pun sama dengan karbohidrat. Benar bahwa kita harus membatasi, namun semuanya pun perlu pembatasan juga, bukan?
Beberapa kemudahan teknologi justru membuat sebagian kaum menengah menjadi minim gerak. Jika suatu saat sudah terkena masalah kesehatan, banyak kaum menengah itu sendiri yang mungkin tercekik dengan biayanya. Apalagi biaya cuci darah. Semoga, mendapat tanggungan setidaknya dari BPJS atau asuransi kesehatan.
Pemilik power yang lemah 2
Masih dalam kemudahan teknologi yang seolah menjadi pisau bermata dua, saya ingin condong membahas dampak mengerikannya.
Dahulu, kebutuhan hiburan begitu terbatas. Kebanyakan hanya berada di televisi.
Sudah beberapa kali saya melihat banyak pekerja di sekitar yang justru asyik menonton film dan serial atau membaca komik saat jam kerja. Hingga ada laporan kalau sebagiannya terlalu mengandalkan AI untuk menyelesaikan tugas mereka kemudian lanjut menonton.
Akibatnya, beberapa perusahaan menganggap daripada membayar orang yang hanya bekerja menggunakan AI, lebih baik perusahaan langsung yang menggunakan AI tersebut.
Di sinilah mulai banyak manusia yang pekerjaannya tersingkirkan oleh AI, sebab manusianya itu sendiri yang tidak memiliki nilai, kalah dengan robot.
Sekali lagi, betul bahwa masih ada yang mencurahkan perhatian mereka kepada pekerjaan, tetapi kalau jumlahnya masih ‘aman’, tidak akan saya menulis artikel ini.
Fenomena yang sekarang, banyak sekali SDM kita yang hanya mampu bekerja di level staf atau junior. Sedari 2017, Indonesia kekurangan tenaga kerja ahli atau selevel manajer.
Oleh sebab inilah, bukan hanya maraknya impor tenaga kerja dari luar, banyak perusahaan pun semakin mempersulit syarat di lowongan kerja. Itu sengaja dan seolah wajib dilakukan perusahaan demi kebaikan perusahaan itu sendiri.
Misalnya, banyak perusahaan yang memberi syarat pada lowongan kerja maksimal usia di bawah 30. Saya beri bocoran, sebenarnya di atas usia 30 bahkan lulusan SMA bisa bekerja di sana, tetapi jumlah pelamar pasti akan sangat banyak dan itu merepotkan staf HRD dalam memilah.
Bayangkan, sebuah perusahaan hanya membuka lowongan untuk 50 orang, namun jika tanpa saringan seperti syarat pendidikan terakhir atau usia, surat lamaran yang masuk bisa sampai 5000 orang.
Kemudian yang kebanyakan dari kita lakukan hanyalah mengeluhkan para pengusaha tersebut bukannya memperbaiki diri sendiri dan berprogres. Padahal jumlah pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan di Indonesia pun jumlahnya masih sangat terbatas.
Artinya, saat sebuah perusahaan memang benar-benar tidak baik atau jahat, pilihan untuk melirik perusahaan lain begitu sedikit.
Justru saat para pengusaha memerlukan tenaga kerja ahli di level manajerial, hampir tidak ada yang melamar meski kuota dan gajinya sangat tinggi.
Tanpa ada intervensi dari pemerintah sekali pun, para investor pun akan berpikir dua kali dengan kualitas SDM di negara yang akan mereka tabur uang mereka.
Penuh ironi
Salah satu perusak produktivitas yang bisa menghancurkan mentalitas hingga kesejahteraan seseorang adalah terlalu sering menggulir media sosial.
Ada saat di mana banyak dari kaum menengah yang mengagumi idola mereka, atau sekadar iri dengan pencapaian sesamanya.
Mereka ingin berlomba mendapatkan lampu sorot di media sosial yang sarat pamer dan beracun itu namun apa daya mereka tidak mampu.
Di sinilah banyak yang jeli melihat kesempatan ini sehingga berjamurlah usaha pinjaman online dan paylater.
Sudah dapat kita tebak. Pada akhirnya banyak kaum menengah yang terjerat hutang berbunga dari para rentenir digital tersebut justru bukan untuk kegiatan primer, melainkan kegiatan pamer.
Padahal harapan awal, pinjaman online ini diharapkan bisa membantu para pengusaha mikro atau kecil menengah dalam mengembangkan usaha mereka. Tetapi, justru berakhir di kegiatan pamer oleh golongan yang kemudian banyak jatuh miskin tersebut.
“Kalau tidak kredit, kapan punyanya?” Klasik.
Ini bukan masalah kredit atau tidaknya, tetapi lebih mengarah kepada mampu atau tidaknya dalam melakukan pembayaran.
Pembunuhan karakter
Seringkali saya melihat di media sosial belum lama ini, bahwa banyak kaum menengah yang menganggap bahwa “bertahan” adalah sebaik-baiknya metode untuk hidup di Indonesia, terkhusus di Jakarta.
Sejujurnya, saya tidak pernah mengenal istilah “bertahan” ini karena bagi saya itu pelemahan mental saya.
Dahulu sewaktu saya masih sangat miskin sampai televisi, kulkas, dan kendaraan tidak punya, pernah makan dengan lauk garam saja, saya tidak pasrah dalam bersabar.
Saya bersabar dengan menerima keterbatasan ekonomi keluarga saya, namun saya tidak sekadar pasrah dan bertahan dalam mengulik hobi saya. Saya memberontak.
Dari dahulu saya ingat kalau saya tertarik mendesain level video game yang dari sana saya harus belajar programming. Di tengah gempuran finansial yang mencekik, saya rela berpuasa demi bisa belajar otodidak di warnet.
Alhamdulillah kini saya telah menjadi CTO di perusahaan yang saya bangun bersama tim.
Belum lagi, maraknya konten bersyukur yang sedikit sekali bermuatan rasa syukurnya itu melemahkan mentalitas kaum menengah.
Konten romantisasi kemiskinan dan ajakan bersyukur banyak menguras rasa iba dari audiens, mengakibatkan tergerusnya semangat produktivitas mereka di hari itu.
Konten media sosial yang menjual rasa kasihan itu cukup beracun. Sebab rasa kasihan akan membuat sebagian orang menjadi sedih dan menyebabkan kualitas kerjanya merosot.
Jika rasa kasihan kita ingin tersalurkan, lebih baik buat anggaran untuk mengalokasikan sebagian gaji kita kepada yang membutuhkan, bukannya malah diromantisasi.
Saya punya beberapa kenalan yang memang benar-benar miskin di Majalengka, dan itu menjadi salah satu prioritas sedekah saya.
Konten romantisasi kemiskinan dan glorifikasi rasa syukur ini banyak yang membuat kaum menengah pada akhirnya terpaksa harus kehilangan ambisi dan pasrah jatuh miskin.
Akhir kata
Tidak banyak orang yang menaruh perhatian pada kasus jatuhnya kaum menengah ke dalam lubang kemiskinan ini kecuali sedikit. Sisanya hanya sibuk menyalahkan pemerintah tok.
Maksudnya, pemerintah pun salah, saya paham. Tetapi mereka pun sebelum menjabat adalah rakyat seperti kita juga, yang sifatnya sebagian besar sama seperti rakyatnya.
Mau sampai kapan budaya salah-menyalahkan ini terjadi? Mengapa bukan budaya improvisasi dan pengenalan masalah yang kita tumbuhkan?
Di akhir kata, banyak yang mencoba peduli kepada kondisi masyarakat tetapi sebagian masyarakatnya itu sendiri yang enggan menghargai diri mereka sendiri.
Dari serentetan paragraf yang dengan lelah saya tulis di atas, sebenarnya mudah agar kita dapat tetap sejahtera di tengah gempuran isu-isu ekonomi. Permasalahannya cuma, apakah ego kita bersedia mendengarkan orang lain yang lebih peduli atau tidak?
Saya pun sering mencari orang-orang yang lebih baik dari saya agar saya ikut terciprat ilmu dan kesejahteraan dari mereka.
Tetapi sayangnya, orang yang lebih baik dari kita cenderung menutup diri karena mereka lelah kepedulian mereka tidak mendapatkan perhatian.
Jadi, kapan kita mulai berbenah dan kembali membangun apa yang telah terserak?
0 Jejak Manis Ditinggalkan
Ke Atas