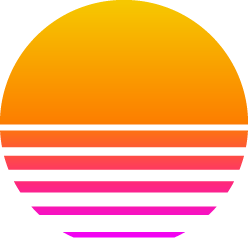Saat ingin berangkat ke Kepulauan Seribu, tepatnya Pulau Tidung, saya bertemu orang di rombongan saya yang terkesima dengan foto-foto di Instagram saya, dan bergumam, “Padahal Indonesia itu indah sebenarnya, kita tapi banyak yang milih liburan ke luar negeri.”
Kata-kata itu mengklik pikiran saya dan menggoda saya untuk membuat artikel yang membahas masalah ini. Setelah saya cari di Google mengenai 20 negara yang paling banyak dikunjungi oleh turis pun, Indonesia tidak termasuk di dalam rentetan negara tersebut. Padahal kita memiliki Raja Ampat, Lombok, Ciletuh, pegunungan-pegunungan, dan budaya-budaya unik.
Sayangnya, Thailand dan Singapura sudah lebih lebar mengembangkan senyum mereka untuk merenggut penghasilan tambahan dari sektor pariwisata.
Ironinya, jangankan turis mancanegara, warganya sendiri saja lebih banyak menghabiskan liburan ke luar negeri. Ada apa?
Standar yang berantakan
Akui saja, negeri kita masih belum ada standar yang pakem untuk memanajemen ini semua, termasuk sektor pariwisata. Kita masih terlalu membangga-banggakan apa yang disebut dengan budaya timur dan kearifan lokal meski pun tidak semua orang lokal memiliki kearifan yang tinggi.
Akibatnya kita masih betah dalam kondisi stagnan karena hal ini, terlalu memberikan toleransi lebih kepada pengelola sektor wisata dan memberikan alasan-alasan yang tidak terlalu masuk di akal seperti membiarkan mereka agar terlihat alami. Inilah mengapa tidak terlalu banyak orang yang mau mengunjungi tempat-tempat wisata yang bejibun di negeri ini.
Padahal untuk Provinsi Jawa Barat saja, atau, Kabupaten Bogor saja, wisata pemandangan dan air terjun hampir-hampir saya tidak dapat menghitungnya karena terlalu banyaknya. Yang satu memiliki watak pengelola yang begini, dan yang satunya lagi memiliki watak pengelola yang begitu. Tidak memiliki standar dan manajemen, sedangkan pemerintah lokalnya terlihat acuh tak acuh. Untuk hal ini pernah saya bahas secara panjang lebar di artikel berikut.
Akses yang buruk
Berapa banyak orang yang tahu Curug Citambur? Lihat foto-foto berikut:



Yup, itu masih di negara tercinta ini, Indonesia. Lokasinya di bagian selatan Cianjur, yang juga banyak berlokasi wisata-wisata alam yang menakjubkan lainnya. Pertanyaannya, mengapa tidak banyak orang yang tahu akan tempat-tempat yang cantik ini, yang tidak begitu jauh dari ibukota jika dibandingkan dengan wisata-wisata yang sudah dikenal dunia?
Lupakan akses angkutan umum. Jalanan yang masih tanah dan berbatu, sempit, hanya dapat dilalui sepeda motor saja, minim penerangan, sarat kejahatan, dan rawan tertutup longsor, benar-benar membuat orang-orang berpikir dua kali untuk mengunjungi tempat ini kecuali orang-orang yang benar-benar haus liburan saja.
Padahal, mudahnya akses saya jadikan salah satu faktor untuk membuat sebuah negara menjadi maju. Lihat Singapura yang hampir cakupan negaranya dapat diakses dengan angkutan umum, atau di Amerika ada Taman Nasional Yosemite yang cukup terpencil namun halte bus bertebaran dengan pemandangan air terjun, atau beberapa destinasi alam di Eropa yang dapat dijangkau dengan mudah dengan kereta api dan bus.
Di kita? Alasan demi alasan terus dilimpahkan dan membuat negeri ini dapat dijuluki dengan negara 1001 alasan. Katanya ingin menjadi negara maju namun enggan dibandingkan dengan negara maju.
Saya tidak ingin muluk-muluk, sekiranya tidak mampu untuk menghadirkan angkutan umum yang jelas ke tempat-tempat indah tersebut, setidaknya jalanan yang dijadikan akses ke sana sudah teraspal dengan baik di mana satu atau dua lubang di jalan masih saya berikan toleransi, contohlah Ciletuh yang sampai-sampai pemerintah pusat harus turun tangan untuk memberikan akses yang baik untuk dapat mencapai puluhan tempat wisata menakjubkan di sana.
Jadi, jangan salahkan beberapa masyarakat kita yang lebih memilih ke Malaysia di mana mereka dapat mengunjungi Batu Caves hanya dengan menaiki KRL meski jadwalnya masih semrawut karena stasiunnya berada tidak jauh dari tempat wisata. Singapura jangan ditanya, karena saya pribadi sulit tersasar di sana.
Seorang bule bilang di situs Quora (maaf saya tidak bookmark), yang berkata kira-kira, “Toba is good, but the road is inaccessible.“
Toleransi dan akhlak yang buruk
Ketika saya mengunjungi Singapura, sangat sulit bagi saya untuk dapat tersasar di negara imut tersebut. Mengapa? Plang petunjuk jalan dibuat jelas dan 4 bahasa, bahkan di tempat yang paling tidak tersentuh sekali pun. Tidak ada budaya, “Masih mending dikasih…”, “Kan bisa begini…”, “Yang penting kan begitu…” dalam budaya Singapura.
Untungnya, Jakarta memiliki Transjakarta dan KRL yang sempat dipimpin oleh orang-orang yang saya sebut dengan Miracle Maker di mana transportasi murah bersubsidi dapat disulap menjadi transportasi mewah dengan pelayanan yang mumpuni di tangan orang yang benar. Mereka menginspirasi saya untuk terus memperbaiki akhlak saya kepada sesama manusia, seperti mengantar orang yang bertanya tentang jalan hingga sampai ke depannya, jadi tidak hanya sekedar memberitahu dengan menunjuk saja. Saya pernah melakukan hal ini hingga 4 kali dan saya merasa lebih dihargai dan lebih berbahagia.
Dahulu, Transjakarta memiliki bus yang sering mogok dan terbakar, pelayanan yang kasar, dan jadwal yang tidak pasti. KRL pun demikian, rombongan kereta (roker) mengerti bagaimana carut-marutnya manajemen KRL sebelum tahun 2012. Sekarang, saya lupa bahwa saya pernah mengalami mimpi buruk yang seperti itu.
Sekarang telah dapat dibayangkan bagaimana manajemen pariwisata yang tidak dikelola resmi oleh pemerintah atau swasta. Beberapa diantaranya saya bahkan bersumpah tidak akan mengunjungi tempat itu lagi. Perlu diingat, orang-orang mengunjungi tempat wisata untuk menyegarkan diri dari repotnya mereka bekerja menghadapi bos atau pelanggan yang galak selama hampir seminggu penuh. Mereka tidak ingin kembali direpotkan oleh pihak pengelola dengan minimnya petunjuk jalan dan tagihan biaya masuk yang berkali-kali.
Jadi biar tidak menemukan hal yang seperti itu, banyak dari kita yang lebih memilih pergi ke Singapura yang benar-benar melayani setiap turis bahkan ketika mereka baru tiba di bandara.
Alokasi yang kurang tepat
Waktu saya ingin ke Curug Ngebul, saya terpesona dengan foto-foto ladang bunga dari Google. Namun setelah saya tiba ke sana, yang saya dapatkan hanyalah bendungan beton yang tidak menarik. Alasannya pelayanan kepada setiap pengunjung. What? Mengapa dananya tidak dialokasikan untuk memperbaiki akses jalan dan memilih untuk membuat sesuatunya menjadi tidak lagi alami?
Begitu pun dengan Curug Malela yang saya tidak jadi ke sana karena katanya jalanannya masih tanah dan berbatu lagi menanjak. Pemerintah lokal hanya merevitalisasinya dengan menambahkan fitur tempat selfie dan menara pandang di sana. Serius, itu hanya membuat area air terjun menjadi tidak alami.
Mengapa mereka tidak membuat jasa shuttle elf atau angkot dari stasiun atau terminal terdekat dengan jam-jam yang sudah fix dan biaya yang terjangkau? Jika tidak mampu untuk menghadirkan fitur tersebut, minimal perhatikan bagaimana aksesnya dahulu seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Itu masih jauh lebih bermanfaat daripada hanya membuat fitur selfie yang setiap dari objek tersebut dikenakan lagi biaya.
Kurangnya rasa nasionalis
Padahal, uang dari tiket pengunjung bisa membantu menyejahterakan daerah setempat juga sebagai salah satu dari pemasukan daerah. Namun banyak dari kita lebih memilih membiarkan tempat tersebut tidak tersentuh. Di sisi lain, beberapa dari kita ada yang mencibir orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan memilih liburan di luar negeri dan acuh mengenai bagaimana manajemen pariwisata yang ada di dalam negeri.
Mengapa kita memiliki sifat yang seperti ini?
Kita ingin orang lain mendengarkan keluh-kesah kita dan menghargai diri kita, namun kita justru tega dan masa bodoh terhadap keluh kesah orang lain. Kita ingin negara kita maju, namun kita hanya membuat hal tersebut hanya terbatas kepada halusinasi semata. Kita terlalu mengandalkan prestasi anak-anak bangsa yang sedikit dan membuat asumsi-asumsi bahwa negara kita akan menjadi negara adidaya sebentar lagi.
Ketika dibandingkan dengan negara lebih maju, berbagai dalih dan alasan dilontarkan. Padahal yang dibandingkan adalah akhlaknya, bukan kecerdasannya. Bahkan tidak sedikit dari kita yang memakai kalimat mengusir ketika dibandingkan dengan negara yang lebih maju seperti, “Ya sudah kenapa enggak minggat aja ke sana!”
Agak miris tetapi… mau bagaimana lagi?
0 Jejak Manis Ditinggalkan
Ke Atas