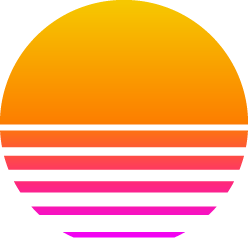Ini adalah artikel yang setengah berisi curhatan saya, setengahnya lagi berisi tentang para pembaca yang juga mengalami hal serupa. Jenius di sini lebih mengarah kepada bakat psikologis, bukan jenius yang pandai menyelesaikan soal-soal olimpiade.
Begini, belum lama, ada psikolog yang menyewa kantor dekat kantor saya. Iseng, saya coba menggunakan jasa psikolog tersebut meski saya harus merogoh kocek hingga Rp400K.
Konsultasi ternyata memakan waktu hingga hampir dua jam.
Bagi saya, hasilnya ternyata sangat positif, bahkan saya begitu puas seakan baru saja mendapatkan siraman rohani. Ibaratnya, hati saya serasa mendapatkan guyuran air es.
Saya baru pertama kali merasakan manisnya “curhat” kepada orang yang memang pernah sungguh-sungguh belajar mendalami tentang kondisi kejiwaan manusia.
Sebenarnya yang saya diskusikan justru lebih mengarah kepada masalah sosial daripada masalah pribadi. Sang psikolog mendengarkan dengan seksama hingga tak terasa sang psikolog juga ikut “curhat” dengan saya. Katanya, mengobrol dengan saya alih-alih konsultasi klien, justru lebih condong kepada sesi saling berbagi.
Sang psikolog juga ternyata tidak memberikan banyak kesimpulan diagnosis karena menurutnya, saya sudah menerapkan apa yang dia ingin sampaikan.
Satu-satunya yang ia ingin sampaikan ke saya, katanya saya adalah seorang yang neurodivergent. Saya memiliki tingkat kepekaan yang tinggi sehingga rawan terkena masalah mental seperti ADHD hingga autisme.
Tapi itu sebenarnya bukan kekurangan dan justru sebuah kelebihan.
Dalam kata lain, saya adalah seorang jenius. Saya terbiasa memikirkan banyak hal di luar kepentingan pribadi saya sampai-sampai saya memahami masalah orang lain lebih baik daripada orang itu sendiri.
Orang seperti saya ini, menurut psikolognya, termasuk jarang kita temukan.
Saya mengakui bahwa jenius di sini bagi saya justru bukanlah sebuah kebanggaan, itu hanyalah fitur psikologis semata. Sama seperti saat seseorang berkata bahwa dia adalah introvert, atau sama seperti saat seseorang bilang bahwa dirinya mudah marah, tidak suka pedas, dan sejenisnya.
Bakat jenius saya ini seolah seperti pisau bermata dua, di satu sisi bisa sebagai bekal dalam menjalani hidup saya dengan segala permasalahannya, namun di satu sisi bisa membuat saya rapuh hingga mudah depresi.
Seperti apa rasanya menjadi orang yang berbakat jenius? Tapi perlu diingat, jika saya diadu dengan peraih juara olimpiade matematika, saya pasti kalah. Karena sekali lagi, jenius saya ini adalah fitur psikologis, bukan keahlian.
Bakat absolut
Masih banyak orang yang bingung mengenai apa bakat mereka. Padahal bakat itu sesederhana melihat biji tumbuhan.
Ketika biji tumbuhan berbakat mangga, maka akan tumbuh pohon mangga. Sesimpel itu.
Tetapi karena banyak orang yang fokus melihat bakat orang lain, mereka jadi tidak mengenali diri mereka sendiri. Jadi jangankan mereka bisa tahu apa bakat mereka.
Analoginya, pohon mangga yang tumbuh di kebun kelapa bisa membuatnya tidak mengenali bahwa dia adalah pohon mangga karena terlalu ikut standar kelapa.
Perlu kita ketahui, dari sisi terluar yang paling mudah kita kenali terlebih dahulu, seperti jenis kelamin, itu sebenarnya sudah bakat. Introvert dan ekstrovert, itu pun bakat. Ada orang yang hobi memperhatikan orang lain, itu bisa jadi sebuah bakat. Ada orang yang dari kecilnya hobi bernyanyi, itu jelas bakat.
Kemudian saat kita melihat orang-orang berbakat yang telah sukses, itu sebenarnya sebab kemampuannya yang membuat mereka sukses, bukan bakatnya.
Ada orang yang berbakat menggambar, tetapi karena tidak pernah ia seriuskan kegiatan menggambarnya bahkan ia menganggap menggambar bukanlah kegiatan yang menghasilkan, maka ia tidak pernah bisa berhasil dengan bakatnya.
Bakat adalah takdir, karena bakatlah manusia menjadi unik sehingga tidak mungkin rezeki seseorang akan tertukar karena uniknya bakat masing-masing.
Seperti yang saya bahas di awal, jenius telah menjadi salah satu bakat saya. Bagaimana ciri-ciri dan dampaknya bagi kehidupan saya?
Terasah dari kecil
Bibi saya dulu cerita, kata beliau pernah waktu saya masih kecil dan belum sekolah, pernah saya yang tadinya bermain di luar rumah tiba-tiba lari masuk ke dalam rumah, masuk kamar dan langsung tidur terlungkup dengan posisi kepala yang masuk ke bantal.
Begitu bibi saya lihat, ternyata saya sedang menangis yang membuat bantal basah. Bibi saya langsung memanggil ibu saya dan saya diinterogasi mengapa bisa tiba-tiba menangis. Mungkin saya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain?
Katanya, saya waktu itu ingin beli mainan di abang-abang, tapi karena takut merepotkan orang tua saya, saya lebih memilih masuk kamar dan menangis. Bibi dan ibu saya tertawa dan bilang itu tidak apa-apa.
Ibu saya pun bilang bahwa saya tidak pernah menuntut macam-macam seperti banyak anak di komplek perumahan saya. Yah, meski saya termasuk orang yang pecicilan alias tidak bisa diam.
Waw, saya lupa kalau saya pernah seperti itu dulu.
Tetapi memang sedari kecil, jika saya melihat sesuatu yang bagi saya nyaman, yang saya pikirkan adalah bagaimana mempertahankan kenyamanan itu agar dapat dinikmati oleh banyak orang, setidaknya orang terdekat saya dahulu.
Pun sebaliknya, saya ingat dahulu rumah saya banyak nyamuk. Ketika saya habis bermain dan pulang selepas magrib, saya melihat ternyata banyak nyamuk berkerumun di atas saluran got sepanjang pemukiman. Pernah saya bawa-bawa obat nyamuk semprot (Bayg*n) dan keliling komplek perumahan hanya untuk menyemprot nyamuk di atas got-got tersebut.
Padahal saya sebenarnya cukup menyemprot nyamuk di got depan rumah saya saja. Entah, saya memikirkan keluarga di rumah lain yang mungkin sama menderitanya seperti saya karena ulah nyamuk-nyamuk itu.
Sampai hari ini pun di mana saya sering pulang sampai malam, saya selalu mematikan lampu jika di kantor hanya ada saya seorang. Sebagai gantinya, saya beli lampu malam yang lebih ekonomis.
Ada rasa tidak betah jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan efisiensi tetapi tidak saya lakukan. Saya tidak tahu, mungkin sudah bakat yang menjadi kebiasaan.
Bahkan indekos saya yang listriknya token sendiri, pernah satu bulan hanya habis 10kWh atau hanya sebesar Rp15 ribu jika 1kWh-nya seharga Rp1.500.
Benar, dalam satu bulan, saya hanya membayar listrik sebesar 15 ribu rupiah saja. Berbeda dengan tetangga-tetangga indekos saya lainnya yang sampai Rp200.000 sebulan.
Saya tidak menyiksa diri saya, tetapi ketika saya merasa tidak perlu menyalakan AC, ya tidak saya nyalakan. Jika ada yang bilang saya melakukan penghematan, justru bukan itu. Karena saya ulangi, ini bukan masalah pribadi saya. Sekali lagi, entah, saya hingga memikirkan hal yang lebih kompleks seperti perubahan iklim dan kira-kira begitulah.
Dua bilah mata pisau
Saya tidak mengenal hidup pasrah.
Maksudnya, saya sabar dalam menghadapi hidup, tetapi sabar saya bukan pasrah. Bahkan saya cenderung memberontak meski saya pada saat itu hidup di bawah garis kemiskinan.
Semiskin apa kami dahulu? Tidak punya kendaraan apa pun, tidak punya TV dan kulkas, makan pernah hanya dengan lauk garam saja, bahkan seringnya saya puasa.
Tetapi saya waktu itu tertarik untuk belajar bahasa pemrograman sehingga uang jajan saya yang memang sudah sedikit, justru saya gunakan untuk ke warnet untuk belajar.
Alhamdulillah, selepas SMA dan selepas wafatnya almarhum bapak kandung saya, dengan game aneh yang saya buat, saya dilirik perusahaan Australia sebagai programmer yang bergaji dua kali UMR pada masanya.
Hingga pada usia 20 tahun, saya keluar dari pekerjaan, dan menjadi CTO di perusahaan yang saya bangun bersama tim, memiliki Rp100 juta di usia 20an tanpa cicilan dan utang apa pun.
Di tengah apa yang saya terima tersebut, justru saya lebih sering bersedih daripada berbahagia. Apakah karena saya kurang bersyukur?
Salah satu kesedihan yang paling sering saya alami adalah kesepian. Padahal, saya punya banyak teman dekat, saudara, dan orang-orang yang menyayangi saya.
Memang kesepian seperti apa yang saya alami? Mengapa bisa saya kesepian di tengah banyak sekali kenikmatan yang saya dapatkan?
Sudah jalannya
Banyak orang yang tidak memahami jika sebagian masalah saya bukanlah masalah pribadi. Bahkan saya bisa bilang jika suatu saat masalah saya pun akan banyak dialami oleh mereka-mereka juga.
Setiap saya utarakan masalah saya, kebanyakan orang justru menyuruh saya agar memikirkan saja diri saya pribadi.
Contohnya pernah dahulu, sekitar tahun 2017 kurang lebih, banyak orang yang memamerkan foto jalan-jalannya hingga seringkali mereka berceloteh, “Indonesia itu indah bro! Jangan di rumah aja!”
Tetapi itu bukan masalah bagi saya. Masalahnya justru saat saya melihat sebuah komentar yang kira-kira seperti ini, “Indonesia sih indah bro, sekarang ke sananya gimana? Apalagi kalau naik angkutan umum, susah bro.”
Sejujurnya, itu membuat saya kepikiran. Padahal itu bukan masalah saya, tetapi mau bagaimana lagi, karena memikirkan masalah sosial itu adalah bakat saya, jadinya lumayan menyiksa saya pada saat itu.
Hingga akhirnya, saya memberanikan diri untuk mencari air terjun di Bogor dan sekitarnya yang dapat dicapai dengan angkutan umum dan saya menemukannya cukup banyak. Di kategori “Tamasya”, ada sesi khusus “wisata dengan angkot”.
Di Instagram saya pun saya posting hasil jalan-jalan saya beserta aksesnya. Tak saya sangka, tiba-tiba saya mendapat ratusan pengikut dan banyak yang katanya terbantu dengan info yang saya berikan di deskripsi.
Itu baru salah satunya dari sekian banyak permasalahan hidup saya.
Saya bilang kepada sang psikolog bahwa saya juga ingin menjadi cuek seperti kebanyakan orang. Sang psikolog justru menggeleng yang artinya itu tidak bisa, itu sudah jadi fitur yang telah mengakar di DNA tubuh saya.
Hikmahnya, beberapa orang menjadi senang curhat kepada saya dan menurut mereka saya tidak pernah menilai secara sepihak masalah-masalah hidup mereka. Sampai-sampai dalam hati saya pernah membatin, “terus saya curhat kepada siapa?”
Pernah suatu ketika, saya menangis di kereta sambil melihat pemandangan indah, sembari bergumam, “Ingin saya menghargai banyak orang secara lebih seperti indahnya pemandangan yang saya saksikan, tetapi sayangnya banyak dari mereka yang tidak menghargai diri mereka sendiri.”
Banyak orang yang seringkali menggampangkan urusan mereka sendiri, jangankan masalah sosial. Mereka pun gemar menyalahkan orang lain, enggan memperbaiki diri, merasa hebat saat menegur orang lain, dan terlalu pasrah.
Ini sampai kepada suatu titik di mana saya menjadi antipati. Maka dari itu saat ada membahas politik yang menyalahkan pemerintah, saya menyalahkan masyarakatnya terlebih dahulu.
Misalnya, ketika mereka membahas pemerintahan korup, maka saya beberkan berita masyarakat yang melakukan pungutan liar, menjarah truk yang terguling, para pengendara yang menerobos lampu merah, trotoar, dan lawan arah.
Masyarakat yang hobi menyalahkan pemerintah, maka pemerintahnya akan hobi menyalahkan masyarakatnya juga. Mau bagaimana lagi, sudah menjadi budaya.
Dan masyarakat ternyata masih banyak yang tidak bisa melihat hal ini. Jadi mau sampai kapan pun jangan berharap ada perubahan yang lebih baik. Sebab pemerintahan yang baik pun tidak akan sanggup memimpin masyarakat yang sebagian besarnya gemar berdrama dan enggan memperbaiki diri.
Secercah harapan
Maka dari itu, saya melampiaskan masalah saya semuanya di kategori Opini di blog Anandastoon ini. Hampir seluruh atau bahkan seluruh artikel di kategori Opini adalah murni curhatan saya sendiri.
Saya pernah mengutarakan kalau saya ingin sekali bertemu orang yang lebih baik dari saya agar ada yang bisa mendengarkan saya dan membimbing saya.
Berbagi permasalahan yang tidak bertepuk sebelah tangan sudah cukup meringankan masalah saya.
Saya pun hobi melawan arus kehidupan demi mempertahankan jati diri saya sendiri. Saya tidak ikut tren, saya tidak mengikuti standar sosial yang tidak cocok dengan saya, dan saya sebenarnya hanya ingin hidup normal.
Tidak mengapa seseorang ingin berbeda dari yang lain karena manusia pada dasarnya sudah memiliki bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Maksud hidup normal di sini adalah, hidup sebagai diri sendiri saja. Hari ini orang-orang terlalu banyak mencari validasi hingga menyiksa diri mereka sendiri dan menyakiti orang lain.
Can’t you just be normal? Maksudnya, fokus saja membenahi diri sendiri karena yang akan menikmati hasilnya ya diri sendiri juga. Apalagi hari ini setelah maraknya kemudahan pinjaman dan media sosial, perilaku manusia banyak yang semakin di luar kendali.
0 Jejak Manis Ditinggalkan
Ke Atas